PENYERAHAN, JATUH TEMPO DAN AKUNTANSINYA
Topik yang diangkat kali ini adalah mengenai sistem penyerahan, termin pembayaran dan akuntansinya. Hal-hal yang dibahas disini antara lain : Jenis-jenis sistem penyerahan, termin pembayaran, tanggal jatuh tempo dan implikasinya terhadap pengakuan penjualan maupun pembelian, serta hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Dan seperti biasa disertai ilustrasi kasus untuk mempermudah pemahaman dan merangsang logika berpikir atas suatu kasus transaksi.
Jika di blog lain yang lebih sering dibahas adalah mixing antara akuntansi dan pajak, di sini, tidak akuntansi dan pajak melulu. Artikel ini akan memadukan antara “Accounting dan Perdagangan”.
Deangan artikel ini saya berharap, anda bisa :
(1). Memahami jenis-jenis sistem penyerahan, dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban sebagai pembeli maupun penjual.
(2). Bisa menumbuhkan logika dasar di dalam mehamai suatu transaksi penjualan maupun pembelian.
(3). Bisa mendeterminasi saat (tanggal) pengakuan atas transaksi penjualan maupun pembelian.
(4). Bisa mendeterminasi tanggal jatuh tempo dengan melihat sistem penyerahan dan termin pembayarannya.
Jika saat ini anda masih berposisi sebagai staff pelaksana di bagaian accounting maupun keuangan, mungkin yang anda butuhkan hanya sebatas bisa mendeterminasi saat (tanggal) pengakuan atas transaksi penjualan atau pembelian.
Okay….. sebagai ilustrasi saya ada 2 contoh kasus yang berbeda :
Basic Case :
Jika kasusunya PT. A berkedudukan di Jakarta, membeli barang dari PT B yang berkedudukan di Surabaya dengan sistem penyerahan Franco Gudang penjual. Barang dikirimkan dari PT B pada tanggal 04 februari 2008, tanggal berapa seharusnya PT B mengakuinya sebagai penjualan, dan tanggal berapa PT A seharusnya mengakuinya sebagai pembelian ?.
Hmm…mungkin sebagian besar dari anda dengan mudah bisa menjawabnya……
Tetapi, coba kita bandingkan dengan kasus yang berikut ini….
Advance Case :
PT. A di Jakarta mengimport buah apel segar dari Australia sebanyak 1 container berukuran 40 feet, tanggal invoice adalah 01 Januari 2008, tanggal PEB adalah tanggal 05 Januari 2008, tanggal fiat muat adalah tanggal 10 Januari 2008, tanggal Bill of Lading adalah tanggal 12 Januari 2008, diperkirakan barang akan tiba di tanjung priok tanggal 22 Januari 2008, barang keluar dari custom tanggal 25 januari 2008, tiba digudang PT. A tanggal 26 Januari 2008. Tetapi karena gelombang pasang, barang baru tiba di di Tanjung periok tanggal 29 Januari dan tiba digudang PT. A baru pada tanggal 03 february 2008.
Sedangkan termin pembayaran adalah 10 hari, jika pembayaran dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo maka penjual akan memberikan discount 5%, setiap satu hari keterlambatan atas pembayaran akan didenda 0.01%.
Jika PT. A baru mentransfer pembayaran pada tanggal 14 Februari 2008 (tanggal slip transfer), uang baru diterima oleh penjual pada tanggal 19 februari 2008. Apakah PT A akan mendapat discount? Atau harus membayar bunga ?.
Oh iya, setelah buah apel dikeluarkan dari petinya, 15% dari keseluruhan buah sudah dalam keadaan berjamur (kelamaan dilaut). Apakah PT. A harus membayar penuh atau proportional sesuai dengan prosentase barang yang bagus saja ?.
Bagaimana anda akan membela kepentingan perusahaan dimana anda bekerja ?, usaha-usaha apa yang akan anda lakukan untuk mencegah perusahaan dari potensi lost seperti ini? apakah cukup hanya mencatat dan mengakui penjualan atau pembelian saja ?. Pastinya tidak. Identifikasi potensi masalahnya, cegah sebelum terjadi, jika tidak bisa dihindari, bagaimana anda akan melakukan advokasi ?.
Jika nanti anda sudah menjadi decision maker & policy maker di accounting maupun keuangan (mudah-mudahan, amin !). Memahami dan menguasai model-model issue seperti ini adalah vital.
Tentu saja artikel ini tidak ditujukan khusus hanya untuk mereka-mereka yang bergelut di dalam jenis usaha export-import saja, atau jenis usaha dagang saja. No !.
Perlu diketahui, bahwa dibidang apapun itu, jenis usaha apapun itu, asalkan ada transaksi maka akan ada penyerahan atau penerimaan, entah itu penyerahan barang, jasa, bahkan royalty sekalipun, dan setiap transaksi pasti mengandung aspek commercial (dagang), aspek administrasi (accounting) dan aspek hukumnya (legal), yang minimal harus anda ketahui basic-nya, sukur-sukur jika bisa mendalaminya.
Jenis-jenis Sistem Penyerahan dan Aspeknya
Ada 5 macam jenis sistem penyerahan yang biasa dipakai di dalam perdagangan, baik perdagangan lokal, antar pulau, maupun export-import, antara lain :
a. Franco Gudang Penjual
Hak dan Kewajiban (Legal)
Penjual berkewajiban menyerahkan barang nya kepada pihak pembeli di gudang penjual. Artinya, segala resiko yang timbul atas barang tersebut setelah keluar dari gudang penjual adalah menjadi tanggungan pihak pembeli. Dengan kata lain, kepemilikan barang sudah berpindah ketangan pembeli saat barang tersebut dikeluarkan dari gudang penjual.
Aspek Komersial (Trade)
Segala biaya yang timbul setelah barang keluar dari gudang penjual adalah beban pembeli (misalnya : biaya angkat/muat, biaya angkut, biaya asuransi jika dilengkapi denga asuransi, biaya bongkar, dan lain-lainnya).
Aspek Akuntansinya (Admin)
Dengan sistem penyerahan ini, di buku penjual, penjualan diakui pada saat barang dikeluarkan dari gudang, demikian halnya di buku pembeli, pembelian dicatat sesuai dengan tanggal surat jalan. Biaya angkat, biaya angkut, biaya asuransi, biaya bongkar menjadi elemen harga pokok dalam Laporan Laba/Rugi pihak pembeli.
b. Free On Board (FOB)
Hak dan kewajiban (Legal)
Penjual berkewajiban menyerahkan barangnya di dek kapal (jika pakai laut) atau truck (jika pakai angkutan darat) atau kabin pesawat cargo (jika memakai angkutan udara). Segala resiko yang timbul setelah barang tersebut dimuat, adalah tanggung jawab pembeli. Sedangkan resiko yang timbul sebelumnya masih menjadi kewajiban penjual. Kepemilikan barang beralih ke tangan pembeli pada saat barang tersebut di muat.
Aspek Komersial (Trade)
Segala biaya yang timbul sejak barang diserahkan di atas alat pengangkutan menjadi tanggungan pembeli, sedangkan biaya-biaya yang timbul sebelumnya adalah tanggungan pihak penjual..
Aspek Akuntansinya (Admin)
Penjual mencacat penjualan (dan pembeli mencatatnya sebagai pembelian) pada saat barang tersebut dimuat (sesuai dengan tanggal muat).
(-) Jika barang dipindahkan melalui jalan darat, maka yang dijadikan patokan tanggal pencatatan adalah tanggal serah terima barang antara penjual dan penyedia transportasi (expedisi/courier) dalam hal ini adalah tanggal resi pengangkutan.
(-) Dalam hal barang dipindahkan melalui jalan udara, maka yang dijadikan tanggal pengakuan penjualan maupun pembelian adalah tanggal Air Way Bill, jika memakai master dan haus AWB, maka yang dijadikan patokan adalah tanggal master airwaybill.
(-) Jika barang dipindahkan melalui jalan laut, maka yang dijadikan tanggal pengakuan penjualan maupun pembelian adalah tanggal Bill Of Lading (B/L), jika memakai master dan haus B/L, maka yang dijadikan patokan adalah master B/L.
c. Cost and Freight (C&F)
Hak dan kewajiban (Legal)
Penjual berkewajiban menyerahkan barang hingga tiba di pelabuhan tujuan (pelabuhan yang disepakati). Kepemilikan barang berpindah dari tangan penjual ke tangan pembeli pada saat barang tiba dipelabuhan yang disepakati (pelabuhan pembeli). Segala resiko yang timbul hingga barang tiba dipelabuhan pembeli adalah tanggung jawab penjual.
Aspek Komersial (Trade)
Penjual menanggung segala biaya yang timbul hingga barang tiba di pelabuhan pembeli atau pelabuhan yang disepakati. Sedangkan biaya yang timbul dari bongkar muatan di pelabuhan, custom clearance, ground handling, trucking (jika ada) menjadi beban pembeli.
Catatan : Khusus beban asuransi (jika ada), masih menjadi tanggungan pihak pembeli.
Aspek Akuntansinya (Admin)
Sedikit sulit mencari reference document (rujukan dokumen?) untuk menentukan tanggal pengakuan atas penjualan dan pembelian. common-nya, pembelian maupun penjualan diakui pada saat kapal (pesawat) tiba di pelabuhan tujuan. Yang paling ideal adalah tanggal custom clearance, karena time windows antara kapal tiba dengan custom clearance biasanya relative singkat. Biaya angkat, biaya angkut (freight) akan diakui sebagai harga pokok di dalam Laporan Laba/Rugi perusahaan penjual. Sedangkan biaya asuransi, biaya clearance, ground handling, dan trucking dari pelabuhan hingga barang di un-load di gudang pembeli diakui sebagai harga pokok oleh perusahaan pembeli.
d. Cost, Insurance & Freight (CIF)
Untuk CIF, ulasan aspek legal, komersial maupun akuntansinya sama seperti pada sistem penyerahan C&F. Yang berbeda hanya di asuransinya. Dalam CIF, pihak penjual WAJIB menyertakan “asuransi perjalanan” atas barang dagangannya. Sehingga di buku penjual, asuransi PASTI ADA di dalam laporan laba ruginya.
e. Franco Gudang Pembeli
Hak dan kewajiban (Legal)
Penjual berkewajiban menyerahkan barangnya di gudang pembeli. Pindah tangan kepemilikan atas barang terjadi di gudang pembeli. Segala resiko yang mungkin terjadi hingga barang tersebut dibongkar di gudang pembeli menjadi tanggung jawab pihak penjual.
Aspek Komersial (Trade)
Segala biaya yang timbul hingga barang tersebut dibongkar digudang pembeli adalah beban pihak penjual.
Aspek Akuntansinya (Admin)
Penjualan maupun pembelian diakui pada tanggal penyerahan barang. Pada Buku perusahaan pembeli, tidak ada transportation cost atau yang terkait, besarnya nilai pembelian hanya sebesar nilai barangnya (plus PPn tentunya jika pembelian dalam negeri). Sedangkan di buku penjual, semua pengeluaran yang membawa barang tersebut hingga tiba di gudang pembeli
Sistem Penyerahan, Termin Pembayaran dan Implikasinya Terhadap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran
Dalam suatu transaksi, pindahnya hak kepemilikan barang/jasa biasanya didahauli/disertai/diikuti oleh penyerahan kompensasi (pembayaran) yang dalam hukum dagang disebut dengan “wan prestasi”, dan TERMIN PEMBAYARAN menjadi hal yang penting dan strategis. Jenis penyerahan apapun itu tidak akan berimplikasi terhadap termin pembayaran jika pembayaran dilakukan di depan (advance payment). Tetapi akan menjadi soal apabila pembayaran tidak dilakukan di depan, antara lain : COD (Cash on delivery), Credit (1 minggu, 10 hari, 30 hari, 45 hari, 60 hari, 90 hari dan lain sebagainya).
Main Question : “What is the due date?” kapan jatuh temponya ?
Antara sistem penyerahan dan due date suatu transaksi jual-beli sangat erat kaitannya. Due date dihitung mulai dari saat penyerahan barang, sedangkan saat penyerahan barang tergantung dari sistem penyerahannya.
Misalnya :
Jika sistem penyerahannya adalah FOB, maka due date dihitung dari saat barang berada di dek truck, kapal atau pesawat (silahkan baca kembali jenis-jenis penyerahan).
(-). Jika termin pembayaran adalah COD (Cash on Delivery), maka biasanya si penjual mengirimkan bukti penyerahan barang ke truck/kapal/pesawat kepada pihak pembeli (by faximile or e-mail) dan pihak pembeli sudah harus mengirimkan pembayaran (wire or else) pada saat bukti penyerahan diterima.
(-). Jika termin pembayaran adalah credit 30 hari, maka tanggal jatuh tempo adalah 30 hari setelah tanggal barang dimuat.
Demikian seterusnya.
Kembali kepada contoh kasus di awal pembahasan, jika anda benar-benar mengikuti pembahasan ini dengan baik, saya yakin anda bisa memecahkannya. Jika tidak, silahkan tulis komentar, pertanyaan, pendapat, atau apapun terkait dengan artikel ini.
Seperti biasa di setiap artikel saya selalu memberikan tips.
Tips :
Bagi anda yang berposisi sebagai : Cahier, Clerk, AP/AR Custodian, Bookkeeper, Chief Accounting, Accounting Manager :
Atas sebuah transaksi pembelian maupun penjualan, tidak cukup hanya memperhatikan tanggal dan nilai transaksi saja, memperhatikan juga :
(-) Sistem Penyerahan
(-) Termin pembayaran
(-) Taxable atau tidak
Bagi anda yang berada di posisi Purchasing & Sales (Staff/Supervisor/Manager) :
Sistem dan termin pembayaran adalah pertimbangan utama anda dalam menilai PRICE QUOTATION dan SALES/PURCHASE.
Guys….”Cheaper/Higher price is not always the king. Quality is the king”, Quality means :
(-) Quality of the merchandize (service) itself
(-) Quality of the delivery’s mode (it should be on time base on the term)
(-) Quality of the payment term
(-) Quality of service after sale (pelayanan purna jual ?
Goodluck everyone !
Senin, 31 Maret 2008
GAJI
Pengantar
Gaji yang bahasa inggrisnya payroll, adalah imbalan yang diberikan oleh pihak yang mempekerjakan kepada pihak pekerja, dalam hubungan yang relatif tetap, maupun dalam bentuk kontrak.
Besarnya Gaji biasanya sudah ditentukan pada saat kesepakatan kerja dilakukan, dan tidak akan berubah sampai dengan adanya kesepakatan baru. Nilainya relatif tetap.
Dalam artikel ini tidak akan dibahas secara mendalam mengenai gaji dilihat dari sudut pandang kepersonaliaan maupun manajemen umum. Pembahasan akan dikonsentrasikan pada aspek-aspek akuntansinya.
Dalam akuntansi, Gaji dimasukkan kedalam golongan biaya, yaitu biaya gaji. Bukan cost.
Elemen-elemen Gaji
Walaupun begitu banyak variasi elemen yang ada pada biaya gaji, akan tetapi pada garis besarnya ada 4 elemen dasar dan 2 elemen tambahan, yang terdiri dari :
1). Gaji Pokok
Gaji Pokok merupakan elemen utama, yang dijadikan dasar pertimbangan mengapa gaji digolongkan kedalam kelompok biaya operasional. Dimana nilainya relatif tetap (paling tidak untuk satu tahun buku). Besarnya nilai pada elemen ini tentunya bervariasi sesuai dengan kemampuan perusahaan, jabatan, masa kerja. Semakin tinggi kemampuan perusahaan, biasanya juga akan menentukan nilai gaji pokok yang relatif lebih tinggi, semakin tinggi suatu jabatan semakin tinggi juga gaji pokoknya, semakin lama masa kerjanya maka kemungkinan kenaikan gaji akan semakin luas yang nantinya berakumulasi menjadi peningkatan nilai dari gaji pokoknya.
2). Lembur
Kebijakan mengenai lembur tidaklah sama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Akan tetapi, pada umumnya lembur biasanya diberikan hanya pada pegawai di tingkatan (level) tertentu saja, yaitu staf (bukan manajer).
3). Tunjangan-Tunjangan
Ada berbagai macam jenis tunjangan, dimana dalam pelaksanaannya sangat tergantung dari kemampuan perusahaan.
a).Tunjangan Jabatan
Jenis tunjangan ini melekat pada suatu jabatan tertentu. Semakin tinggi suatu jabatan, tunjangan inipun semakin tinggi (sampai pada batas tertentu).
b).Tunjangan Kesehatan
Tunjangan kesehatan tergolong tunjangan yang paling banyak disediakan oleh perusahaan setelah tunjangan jabatan. Dalam praktiknya tunjangan kesehatan ini diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya ; Penggantian biaya kesehatan, pembebasan biaya pembelian obat, dan lain sebagainya.
c).Tunjangan Asuransi
Tunjangan asuransi yang paling lumrah dipakai di Indonesia adalah produk-produk asuransi yang disediakan oleh PT. Jamsostek (Persero)
d). Dan Tunjangan lain (yang bervariasi dan tidak umum dipakai)
4). Potongan-potongan
Potongan atas Gaji yang paling dasar adalah potongan Pajak Penghasilan (PPh), Premi asuransi yang ditanggung oleh pegawai,.
5). Bonus & Insentif
Bonus & insentif merupakan elemen tambahan, biasanya disediakan oleh jenis perusahaan tertentu dan untuk pegawai tertentu saja, yaitu distributor, bank, finance dan perusahaan sejenis yang operasionalnya berorientasikan target. Elemen ini nilainya tidak tetap.
Perlakuan Akuntansi atas Gaji
1). Penilaian (Penghitungan Gaji)
Gaji dihitung dengan memformulasikan elemen-elemen yang ada pada gaji. Dari semua elemen yang ada, hanya elemen potongan lah yang menjadi factor pengurang besarnya nilai gaji. Sedangkan elemen lainnya merupakan faktar penambah besarnya nilai Gaji.
Gaji dapat diformulasikan sebagai berikut :
[Gaji Pokok] + [Lembur] + [Tunjangan] - [Potongan] + [Bonus/Insentif]
Dengan formula ini, besarnya biaya gaji yang akan timbul dapat ditentukan.
2). Pengakuan Atas Gaji
Gaji yang dibayarkan dengan system transfer diakui apada saat transfer dilaksanakan, gaji yang dibayarkan dengan menggunakan check diakui pada saat check tersebut dicairkan oleh penerima gaji, sedangkan gaji yang dibayarkan dalam bentuk tunai (cash) diakui pada saat gaji diserahkan. Besarnya biaya gaji yang diakui adalah sebesar nilai hasil formulasi di atas.
3). Pencatatan (Jurnal Penggajian)
Gaji dicatat pada saat pengakuannya, yaitu : sesuai tanggal yang tertera di slip transfer, di slip gaji, tanggal check (tergantung bentuk gaji yang diberikan).
Adapun jurnal atas gaji adalah sebagai berikut :
Pada saat penggajian :
Debit : Biaya Gaji
Kredit : Kas dan Utang PPh
Contoh :
Biaya Gaji (Debit) : Rp 100,000,000,-
Kas (Kredit) : Rp 90,000,000,-
Utang PPh Pasal 21 (Kredit) : Rp 10,000,000,-
Pada saat penyetoran PPh :
Utang PPh Pasal 21 (Debit) : Rp 10,000,000
Kas (Kredit) : Rp 10,000,000
4) Pelaporan Gaji
Pada Laporan Rugi Laba, Gaji termasuk di dalam kelompok besar biaya operasional dan dinyatakan di dalam akun Biaya Gaji, yang nantinya akan mempengaruhi besar-kecilnya laba atau rugi perusahaan. Pernyataan Laba rugi akan memberi kontribusi terhadap Akun laba ditahan (retained earning) pada Neraca.
Prosedur Penggajian
a). Penghitungan Gaji
Penghitungan gaji didahului oleh pengumpulan data-data yang nantinya akan dijadikan dasar perhitungan. Sumber data penghitungan gaji berasal dari bagian personalia yang seharusnya diserahkan begitu tutup buku penggajian dilakukan (biasanya 1 minggu sebelum tanggal penggajian). Adapun data-data yang diperlukan yaitu :
Untuk menentukan besarnya Gaji Pokok, Tunjangan dan Potongan : Daftar Karyawan (lengkap dengan jabatan dan masa kerjanya), daftar absensi, daftar cuti, daftar libur berbayar.
Untuk menentukan Bonus atau insentif : Daftar yang dijadikan dasar perhitungan (Daftar Penjualan dari masing-masing salesman).
Formula yang dipakai adalah seperti yang telah disebutkan pada sub pokok bahasan di atas.
Setelah perhitungan selesai dilakukan, hendaknya dilakukan pemeriksaan dan penelitian kembali sebelum dimintakan persetujuan kepada Manajer Personalia.
b). Persetujuan Gaji
Daftar Gaji diajukan oleh Manajer Personalia kepada Direktur, dengan tembusan kepada General Manager dan atau Financial Controller. Financial Controller maupun General Manager akan melakukan penelitian baik itu secara mengkhusu dan terperinci maupun umum, yang sangat tergantung dari Daftar Gaji yang diajukan (apakah daftar gaji itu dinilai wajar atau tidak). Setelah diteliti, jika dapat disetujui maka Financial Controller atau General Manager akan memberikan rekomendasi kepada direktur untuk disetujui, Sedangkan jika dianggap tidak wajar, maka Financial Controller atau General Manager berhak untuk menahannya sampai dijelaskan dan atau dilakukan perbaikan-perbaikan seperlunya.
c). Permintaan Kas untuk Penggajian
Dalam hal Daftar Gaji disetujui dan telah disahkan, maka daftar Gaji tersebut akan diserahkan kepada Bagian Accounting sebagai dasar untuk permintaan kas penggajian. Bagian Accounting akan menyiapkan Kas sesuai dengan permintaan. Permintaan Kas disertai daftar gaji yang telah disahkan hendaknya telah diterima selambat-lambatnya 2 hari sebelum tanggal penggajian.
Untuk gaji yang akan dibayarkan dalam bentuk tunai, akan dibuatkan 1 check tunai saja untuk semuanya. Untuk gaji yang dibayarkan dalam bentuk check, akan dibuatkan check masin-masing untuk satu karyawan. Sedangkan untuk gaji yang dibayarkan melalui transfer, maka akan disiapkan satu daftar perintah transfer kepada bank.
d). Pembagian Gaji
Gaji dibagikan atau ditransfer tepat pada tanggal pengajian, dibagikan oleh kasir perusahaan, disaksikan oleh staf personalia. Diawasi oleh Chief Accounting dan Manajer Personalia. Hal ini penting, agar jika diperlukan dapat memberikan penjelasan yang sesuai kepada pegawai yang membutuhkan penjelasan.
e). Pencatatan Penggajian
Setelah pembayaran gaji selesai dilaksanakan, maka Book Keeper akan melakukan pencatatan dengan memposting ayat-ayat jurnal yang sesuai (lihat di sub pokok pembahasan sebelumnya).
f). Pemeriksaan Penggajian
Proses selanjutnya adalah proses pemeriksaan. Pemeriksaan akan dilakukan oleh Financial Controller. Adapun pemeriksaan yang dilakukan, yaitu dengan membandingkan antara daftar gaji yang telah desetujui dengan pengeluaran kas, Slip Gaji, sisa fisik uang yang masih ada di kasir, Bukti pemotongan PPh Pasal 21, untuk kemudian dibandingkan dengan General Ledger Detail yang di print-out oleh Book Keeper. Apabila tidak ditemukan kesalahan atau ketidak wajaran, maka Financial Controller akan membuat pernyataan wajar atas penggajian tersebut, sekaligus memberikan ijin untuk ditutup.
g). Penutupan dan Arsip Penggajian
Proses akhir dari penggajian adalah penutupan, dimana penutupan dilakukan apabila pemeriksaan telah selesai dilaksanakan oleh Financial Controller. Selanjutnya semua bukti yang terkait dengan penggajian (Daftar Gaji, Slip Gaji, Bukti Tranfer, Bonggol Check dan Print Out General Ledger Detail yang disahkan oleh Financial Controller) diarsipkan ke dalam masing-masing binder yang telah ditentukan.
Gaji yang bahasa inggrisnya payroll, adalah imbalan yang diberikan oleh pihak yang mempekerjakan kepada pihak pekerja, dalam hubungan yang relatif tetap, maupun dalam bentuk kontrak.
Besarnya Gaji biasanya sudah ditentukan pada saat kesepakatan kerja dilakukan, dan tidak akan berubah sampai dengan adanya kesepakatan baru. Nilainya relatif tetap.
Dalam artikel ini tidak akan dibahas secara mendalam mengenai gaji dilihat dari sudut pandang kepersonaliaan maupun manajemen umum. Pembahasan akan dikonsentrasikan pada aspek-aspek akuntansinya.
Dalam akuntansi, Gaji dimasukkan kedalam golongan biaya, yaitu biaya gaji. Bukan cost.
Elemen-elemen Gaji
Walaupun begitu banyak variasi elemen yang ada pada biaya gaji, akan tetapi pada garis besarnya ada 4 elemen dasar dan 2 elemen tambahan, yang terdiri dari :
1). Gaji Pokok
Gaji Pokok merupakan elemen utama, yang dijadikan dasar pertimbangan mengapa gaji digolongkan kedalam kelompok biaya operasional. Dimana nilainya relatif tetap (paling tidak untuk satu tahun buku). Besarnya nilai pada elemen ini tentunya bervariasi sesuai dengan kemampuan perusahaan, jabatan, masa kerja. Semakin tinggi kemampuan perusahaan, biasanya juga akan menentukan nilai gaji pokok yang relatif lebih tinggi, semakin tinggi suatu jabatan semakin tinggi juga gaji pokoknya, semakin lama masa kerjanya maka kemungkinan kenaikan gaji akan semakin luas yang nantinya berakumulasi menjadi peningkatan nilai dari gaji pokoknya.
2). Lembur
Kebijakan mengenai lembur tidaklah sama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Akan tetapi, pada umumnya lembur biasanya diberikan hanya pada pegawai di tingkatan (level) tertentu saja, yaitu staf (bukan manajer).
3). Tunjangan-Tunjangan
Ada berbagai macam jenis tunjangan, dimana dalam pelaksanaannya sangat tergantung dari kemampuan perusahaan.
a).Tunjangan Jabatan
Jenis tunjangan ini melekat pada suatu jabatan tertentu. Semakin tinggi suatu jabatan, tunjangan inipun semakin tinggi (sampai pada batas tertentu).
b).Tunjangan Kesehatan
Tunjangan kesehatan tergolong tunjangan yang paling banyak disediakan oleh perusahaan setelah tunjangan jabatan. Dalam praktiknya tunjangan kesehatan ini diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya ; Penggantian biaya kesehatan, pembebasan biaya pembelian obat, dan lain sebagainya.
c).Tunjangan Asuransi
Tunjangan asuransi yang paling lumrah dipakai di Indonesia adalah produk-produk asuransi yang disediakan oleh PT. Jamsostek (Persero)
d). Dan Tunjangan lain (yang bervariasi dan tidak umum dipakai)
4). Potongan-potongan
Potongan atas Gaji yang paling dasar adalah potongan Pajak Penghasilan (PPh), Premi asuransi yang ditanggung oleh pegawai,.
5). Bonus & Insentif
Bonus & insentif merupakan elemen tambahan, biasanya disediakan oleh jenis perusahaan tertentu dan untuk pegawai tertentu saja, yaitu distributor, bank, finance dan perusahaan sejenis yang operasionalnya berorientasikan target. Elemen ini nilainya tidak tetap.
Perlakuan Akuntansi atas Gaji
1). Penilaian (Penghitungan Gaji)
Gaji dihitung dengan memformulasikan elemen-elemen yang ada pada gaji. Dari semua elemen yang ada, hanya elemen potongan lah yang menjadi factor pengurang besarnya nilai gaji. Sedangkan elemen lainnya merupakan faktar penambah besarnya nilai Gaji.
Gaji dapat diformulasikan sebagai berikut :
[Gaji Pokok] + [Lembur] + [Tunjangan] - [Potongan] + [Bonus/Insentif]
Dengan formula ini, besarnya biaya gaji yang akan timbul dapat ditentukan.
2). Pengakuan Atas Gaji
Gaji yang dibayarkan dengan system transfer diakui apada saat transfer dilaksanakan, gaji yang dibayarkan dengan menggunakan check diakui pada saat check tersebut dicairkan oleh penerima gaji, sedangkan gaji yang dibayarkan dalam bentuk tunai (cash) diakui pada saat gaji diserahkan. Besarnya biaya gaji yang diakui adalah sebesar nilai hasil formulasi di atas.
3). Pencatatan (Jurnal Penggajian)
Gaji dicatat pada saat pengakuannya, yaitu : sesuai tanggal yang tertera di slip transfer, di slip gaji, tanggal check (tergantung bentuk gaji yang diberikan).
Adapun jurnal atas gaji adalah sebagai berikut :
Pada saat penggajian :
Debit : Biaya Gaji
Kredit : Kas dan Utang PPh
Contoh :
Biaya Gaji (Debit) : Rp 100,000,000,-
Kas (Kredit) : Rp 90,000,000,-
Utang PPh Pasal 21 (Kredit) : Rp 10,000,000,-
Pada saat penyetoran PPh :
Utang PPh Pasal 21 (Debit) : Rp 10,000,000
Kas (Kredit) : Rp 10,000,000
4) Pelaporan Gaji
Pada Laporan Rugi Laba, Gaji termasuk di dalam kelompok besar biaya operasional dan dinyatakan di dalam akun Biaya Gaji, yang nantinya akan mempengaruhi besar-kecilnya laba atau rugi perusahaan. Pernyataan Laba rugi akan memberi kontribusi terhadap Akun laba ditahan (retained earning) pada Neraca.
Prosedur Penggajian
a). Penghitungan Gaji
Penghitungan gaji didahului oleh pengumpulan data-data yang nantinya akan dijadikan dasar perhitungan. Sumber data penghitungan gaji berasal dari bagian personalia yang seharusnya diserahkan begitu tutup buku penggajian dilakukan (biasanya 1 minggu sebelum tanggal penggajian). Adapun data-data yang diperlukan yaitu :
Untuk menentukan besarnya Gaji Pokok, Tunjangan dan Potongan : Daftar Karyawan (lengkap dengan jabatan dan masa kerjanya), daftar absensi, daftar cuti, daftar libur berbayar.
Untuk menentukan Bonus atau insentif : Daftar yang dijadikan dasar perhitungan (Daftar Penjualan dari masing-masing salesman).
Formula yang dipakai adalah seperti yang telah disebutkan pada sub pokok bahasan di atas.
Setelah perhitungan selesai dilakukan, hendaknya dilakukan pemeriksaan dan penelitian kembali sebelum dimintakan persetujuan kepada Manajer Personalia.
b). Persetujuan Gaji
Daftar Gaji diajukan oleh Manajer Personalia kepada Direktur, dengan tembusan kepada General Manager dan atau Financial Controller. Financial Controller maupun General Manager akan melakukan penelitian baik itu secara mengkhusu dan terperinci maupun umum, yang sangat tergantung dari Daftar Gaji yang diajukan (apakah daftar gaji itu dinilai wajar atau tidak). Setelah diteliti, jika dapat disetujui maka Financial Controller atau General Manager akan memberikan rekomendasi kepada direktur untuk disetujui, Sedangkan jika dianggap tidak wajar, maka Financial Controller atau General Manager berhak untuk menahannya sampai dijelaskan dan atau dilakukan perbaikan-perbaikan seperlunya.
c). Permintaan Kas untuk Penggajian
Dalam hal Daftar Gaji disetujui dan telah disahkan, maka daftar Gaji tersebut akan diserahkan kepada Bagian Accounting sebagai dasar untuk permintaan kas penggajian. Bagian Accounting akan menyiapkan Kas sesuai dengan permintaan. Permintaan Kas disertai daftar gaji yang telah disahkan hendaknya telah diterima selambat-lambatnya 2 hari sebelum tanggal penggajian.
Untuk gaji yang akan dibayarkan dalam bentuk tunai, akan dibuatkan 1 check tunai saja untuk semuanya. Untuk gaji yang dibayarkan dalam bentuk check, akan dibuatkan check masin-masing untuk satu karyawan. Sedangkan untuk gaji yang dibayarkan melalui transfer, maka akan disiapkan satu daftar perintah transfer kepada bank.
d). Pembagian Gaji
Gaji dibagikan atau ditransfer tepat pada tanggal pengajian, dibagikan oleh kasir perusahaan, disaksikan oleh staf personalia. Diawasi oleh Chief Accounting dan Manajer Personalia. Hal ini penting, agar jika diperlukan dapat memberikan penjelasan yang sesuai kepada pegawai yang membutuhkan penjelasan.
e). Pencatatan Penggajian
Setelah pembayaran gaji selesai dilaksanakan, maka Book Keeper akan melakukan pencatatan dengan memposting ayat-ayat jurnal yang sesuai (lihat di sub pokok pembahasan sebelumnya).
f). Pemeriksaan Penggajian
Proses selanjutnya adalah proses pemeriksaan. Pemeriksaan akan dilakukan oleh Financial Controller. Adapun pemeriksaan yang dilakukan, yaitu dengan membandingkan antara daftar gaji yang telah desetujui dengan pengeluaran kas, Slip Gaji, sisa fisik uang yang masih ada di kasir, Bukti pemotongan PPh Pasal 21, untuk kemudian dibandingkan dengan General Ledger Detail yang di print-out oleh Book Keeper. Apabila tidak ditemukan kesalahan atau ketidak wajaran, maka Financial Controller akan membuat pernyataan wajar atas penggajian tersebut, sekaligus memberikan ijin untuk ditutup.
g). Penutupan dan Arsip Penggajian
Proses akhir dari penggajian adalah penutupan, dimana penutupan dilakukan apabila pemeriksaan telah selesai dilaksanakan oleh Financial Controller. Selanjutnya semua bukti yang terkait dengan penggajian (Daftar Gaji, Slip Gaji, Bukti Tranfer, Bonggol Check dan Print Out General Ledger Detail yang disahkan oleh Financial Controller) diarsipkan ke dalam masing-masing binder yang telah ditentukan.
PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA (Customer's Cash Advance)
Apa itu Pendapatan Diterima di Muka? Mengapa Pendapatan Diterima di Muka? Kapan suatu pendapatan diakui sebagai Pendapatan Diterima di Muka? Kapan kita akui sebagai penjualan atau pendapatan jasa saja?. Jika terjadi ketidak-sesuaian pengakuan pendapatan, apa yang harus dilakukan?. Semuanya saya bahas di artikel ini.
Pengertian Pendapatan Diterima di Muka
Begitu straight forward, "Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan atas suatu barang/jasa yang belum diserahkan".
Kedengarannya sangat sederhana dan mudah bukan?
Kenyataannya, di masa sekarang ini, dimana sektor usaha semakin variatif, jenis barang/jasa, sistem pembayaran, serta alat pembayaran yang semakin bervariasi membuat penerapan akuntansi menjadi semakin kompleks dan rumit, tidak sederhana lagi, diperlukan mix and match. Akan tetapi sesungguhnya, jika konsep dasar akuntansi sudah dipahami dengan benar dan lengkap, dibolak-balik bagaimanapun, benang merahnya akan tetap sama.
Pengakuan Atas Pendapatan Diterima di Muka
Perhatikan contoh kasus berikut ini :
Pada tanggal 25 Februari 2008, bapak Andre menerima pesanan 1000 pcs jacket, @50,000/pc. pesanan rencananya akan dikirimkan secara bertahap dengan jadwal sebagai berikut :

Atas pesanan tersebut, dihari yang sama bapak Andre menerima pembayaran sebesar Rp 30,000,000,- Sedangkan sisa pembayaran akan diterima setiap kali barang diserahkan.
Atas transaksi di atas, pada tanggal 25 Februari 2008 Bapak Andre melakukan pencatatan sebagai berikut :
[Debit]. Kas = Rp 30,000,000,-
[Debit]. Piutang = Rp 20,000,000,-
[Credit]. Penjualan = Rp 50,000,000,- (50,000 x 1000 pcs)
Apakah jurnal di atas sudah sesuai ?
Jawabannya, sementara kita pending dahulu :-) kita masuk ke pembahasan berikutnya.
Pengakuan atas Penjualan atau Pendapatan Jasa
Penjualan atau pendapatan jasa diakui paling cepat pada saat barang dikirimkan atau jasa diserahkan, selambat-lambatnya pada saat kas diterima. Dalam hal barang sudah diserahkan tetapi kas (payment) belum dietrima, maka penjualan di catat dengan mendebit rekening piutang, sedangkan jika kas sudah diterima, maka penjualan dicatat dengan mendebit rekening kas tentunya. Menurut PSAK berapa ?, silahkan dibaca sendiri, karena saya tidak hafal dan saya merasa tidak perlu untuk menghafalnya :-)
Dalam kasus di atas, bukankah Kas sudah diterima? Berarti penjualan sudah bisa diakui bukan? benar kas sudah diterima, tetapi barang/jasa belum diserahkan, sehingga belum bisa diakui sebagai penjualan.
Mengapa kalau barang/jasa belum diserahkan sebaiknya penjualan/pendapatan jasa jangan diakui dahulu?
Di dalam akuntansi berlaku prinsip kesesuaian, dapat disandingkan (The Matching Principle), artinya; setiap pengorbanan ekonomis (pengeluaran/biaya/cost) yang diakui hendaknya disandingkan dengan manfaat (gain) yang ditimbulkan pada periode yang sama. Dengan kalimat sederhana; setiap biaya yang timbul hendaknya dapat disandingkan dengan pendapatan/penjualan yang diperoleh. Begitu juga sebaliknya, untuk setiap pendapatan yang diakui mestinya dapat disandingkan dengan cost atau expense yang timbul.
Pada contoh kasus bapak Andre di atas, bapak Andre sudah mengakui pendapatan padahal barang (jacket) belum diserahkan kepada pihak pembeli. Bapak andre belum berproduksi, bukankah pesanan baru saja diterima?, praktis belum ada cost maupun expense yang timbul akibat pesanan barang tersebut.
Ekses apa yang timbul sebagai akibat dari ketidak-sesuaian pencatatan bapak Andre di atas ?
Karena pada tanggal 25 Februari membukukan penjualan sebesar Rp 30,000,000 padahal belum ada cost maupun expense yang timbul, maka pada Laporan Laba/Rugi Periode 01 s/d 29 Februari 2008 bapak andre akan terlihat laba setidaknya Rp 30,000,000. Sedangkan di periode berikutnya (01 s/d 31 Maret 2008) bapak andre akan terus menerus mencatat cost maupun expense untuk menyelesaikan pesanan yang pembayarannya sudah dibukukan pada Laporan Laba/Rugi periode sebelumnya. Sehingga pada penutupan buku bulan Maret 2008 bapak andre akan membukukan Rugi (Lost) yang setidak-tidaknya sama dengan cost dan expense yang timbul selama periode tersebut. Jika ditampilkan dalam grafik, maka performance trend yang dihasilkan akan kelihatan aneh alias tidak wajar. Terjadi fluktuasi yang drastis dari periode Februari ke periode Maret 2008.
Bagaimana dan kapan melakukan pengakuan yang lebih sesuai agar trend laba rugi wajar?
Tips:
Setiap transaksi pendapatan yang belum menimbulkan biaya dicatat di rekening yang ada di Neraca.
Dalam contoh kasus bapak Andre di atas sebaiknya dicatat (perhatikan jadwal pengiriman dan rencana pembayaran) di atas.
Pada tanggal 25 Feb 2008 (saat menerima pembayaran pertama) di catat:
[Debit]. Kas = Rp 30,000,000,-
[Credit]. Pendapatan diterima dimuka = Rp 30,000,000
Pada tanggal 1 Maret 2008 (saat pengiriman barang pertama) di catat:
[Debit]. Harga Pokok Penjualan
[Credit]. Persediaan
[Debit]. Pendapatan Diterima di Muka = Rp 15,000,000
[Credit]. Penjualan = Rp 15,000,000
Catatan: Penjualan mulai diakui pada saat barang dikirimkan (diserahkan), DAN… atas penjualan yang terjadi SUDAH dapat disandingkan dengan cost yang timbul di periode yang sama, yaitu Harga Pokok Penjualan. Perhatikan Pendapatan diterima Di Muka, dengan jurnal pada tanggal 01 Maret 2008, maka saldo Pendapatan Diterima di Muka tinggal sebesar Rp 15,000,000 saja.
Pada tanggal 15 Maret 2008 (saat pengiriman barang ke-2) dicatat:
[Debit]. Harga Pokok Penjualan
[Credit]. Persediaan
[Debit]. Pendapatan Diterima di Muka = Rp 15,000,000
[Credit]. Penjualan = Rp 15,000,000
Catatan: Lagi-lagi penjualan dicatat sebesar Rp 15,000,000 dengan mendebit rekening Pendapatan Diterima di Muka, sehingga total penjualan telah mencapai Rp 30,000,000,- dan saldo rekening Pendapatan Diterima di Muka menjadi 0 (nol).
Pada tanggal 30 Maret 2008 (saat pengiriman terakhir dilakukan), pembayaran belum diterima, sehingga dicatat:
[Debit]. Harga Pokok Penjualan
[Credit]. Persediaan
[Debit]. Piutang = Rp 20,000,000
[Credit]. Penjualan = Rp 20,000,000
Pada tanggal 01 April 2008 (saat pembayaran diterima) dicatat:
[Debit]. Kas = Rp 20,000,000,-
[Credit]. Piutang = Rp 20,000,000,-
Catatan: Pada pengiriman barang yang ketiga (terakhir) ini, barang diserahkan, dan penjualan dapat dilawankan dengan Harga Pokok Penjualannya, sehingga wajar jika diakui sebagai penjualan. Jikapun kas belum diterima, toh bisa mendebit rekening Piutang.
Kesimpulan
Jika kita perhatikan jurnal-jurnal diatas, dapat kita lihat bahwa pada setiap pengakuan Penjualan selalu bersandingan dengan pengakuan Harga Pokok Penjualan (cost factor) dilegalisasi dengan berpindahnya fisik barang yang tercermin dalam rekening persediaan yang saldonya juga semakin berkurang (berada di sisi kredit). Inilah “Essential of The Matching Principle” didalam akuntansi.
Apakah ketidak-sesuaian pencatatan yang dilakukan oleh bapak Andre diawal transaksi (saat penerimaan pembayaran pertama) perlu dibuatkan adjustment entry?
Jawaban saya : "It depends on………"
Tergantung, jika pada pengiriman barang pertama dan kedua bapak Andre hanya mengakui Harga Pokok Penjualan dengan mengkredit rekening Persediaan SAJA, tanpa mencatat penjualan lagi. Maka adjustment entry rasanya TIDAK MUTLAK DIPERLUKAN.
Mengapa ?
Bapak Andre hanya terlalu dini mengakui penjualan, yang dalam akuntansi diistilahkan dengan “EARLY REVENUE RECOGNITION”, Early Revenue Recognition MASIH tergolong “MIS-STATEMENT”, belum termasuk “MATERIAL ISSUE”. Toh terjadi masih dalam tahun buku yang sama, dimana Revenue Overstatement yang terjadi dibulan Februari akan terimbangi oleh Cost Overstatement di bulan Maret. Hanya saja trend-nya menjadi tidak wajar. Lain cerita jika kasusnya "PREMATURE REVENUE RECOGNITION" yaitu pengakuan pendapatan atas suatu potensi pendapatan atau yang masih berupa commitment, maka itu akan tergolong "Material Issue". Hanya saja kebiasaan pencatatan seperti yang dilakukan oleh bapak Andre pada contoh kasus ini, sebaiknya dihindari, karena akan merepotkan jika terjadi di akhir tahun buku.
Pengertian Pendapatan Diterima di Muka
Begitu straight forward, "Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan atas suatu barang/jasa yang belum diserahkan".
Kedengarannya sangat sederhana dan mudah bukan?
Kenyataannya, di masa sekarang ini, dimana sektor usaha semakin variatif, jenis barang/jasa, sistem pembayaran, serta alat pembayaran yang semakin bervariasi membuat penerapan akuntansi menjadi semakin kompleks dan rumit, tidak sederhana lagi, diperlukan mix and match. Akan tetapi sesungguhnya, jika konsep dasar akuntansi sudah dipahami dengan benar dan lengkap, dibolak-balik bagaimanapun, benang merahnya akan tetap sama.
Pengakuan Atas Pendapatan Diterima di Muka
Perhatikan contoh kasus berikut ini :
Pada tanggal 25 Februari 2008, bapak Andre menerima pesanan 1000 pcs jacket, @50,000/pc. pesanan rencananya akan dikirimkan secara bertahap dengan jadwal sebagai berikut :

Atas pesanan tersebut, dihari yang sama bapak Andre menerima pembayaran sebesar Rp 30,000,000,- Sedangkan sisa pembayaran akan diterima setiap kali barang diserahkan.
Atas transaksi di atas, pada tanggal 25 Februari 2008 Bapak Andre melakukan pencatatan sebagai berikut :
[Debit]. Kas = Rp 30,000,000,-
[Debit]. Piutang = Rp 20,000,000,-
[Credit]. Penjualan = Rp 50,000,000,- (50,000 x 1000 pcs)
Apakah jurnal di atas sudah sesuai ?
Jawabannya, sementara kita pending dahulu :-) kita masuk ke pembahasan berikutnya.
Pengakuan atas Penjualan atau Pendapatan Jasa
Penjualan atau pendapatan jasa diakui paling cepat pada saat barang dikirimkan atau jasa diserahkan, selambat-lambatnya pada saat kas diterima. Dalam hal barang sudah diserahkan tetapi kas (payment) belum dietrima, maka penjualan di catat dengan mendebit rekening piutang, sedangkan jika kas sudah diterima, maka penjualan dicatat dengan mendebit rekening kas tentunya. Menurut PSAK berapa ?, silahkan dibaca sendiri, karena saya tidak hafal dan saya merasa tidak perlu untuk menghafalnya :-)
Dalam kasus di atas, bukankah Kas sudah diterima? Berarti penjualan sudah bisa diakui bukan? benar kas sudah diterima, tetapi barang/jasa belum diserahkan, sehingga belum bisa diakui sebagai penjualan.
Mengapa kalau barang/jasa belum diserahkan sebaiknya penjualan/pendapatan jasa jangan diakui dahulu?
Di dalam akuntansi berlaku prinsip kesesuaian, dapat disandingkan (The Matching Principle), artinya; setiap pengorbanan ekonomis (pengeluaran/biaya/cost) yang diakui hendaknya disandingkan dengan manfaat (gain) yang ditimbulkan pada periode yang sama. Dengan kalimat sederhana; setiap biaya yang timbul hendaknya dapat disandingkan dengan pendapatan/penjualan yang diperoleh. Begitu juga sebaliknya, untuk setiap pendapatan yang diakui mestinya dapat disandingkan dengan cost atau expense yang timbul.
Pada contoh kasus bapak Andre di atas, bapak Andre sudah mengakui pendapatan padahal barang (jacket) belum diserahkan kepada pihak pembeli. Bapak andre belum berproduksi, bukankah pesanan baru saja diterima?, praktis belum ada cost maupun expense yang timbul akibat pesanan barang tersebut.
Ekses apa yang timbul sebagai akibat dari ketidak-sesuaian pencatatan bapak Andre di atas ?
Karena pada tanggal 25 Februari membukukan penjualan sebesar Rp 30,000,000 padahal belum ada cost maupun expense yang timbul, maka pada Laporan Laba/Rugi Periode 01 s/d 29 Februari 2008 bapak andre akan terlihat laba setidaknya Rp 30,000,000. Sedangkan di periode berikutnya (01 s/d 31 Maret 2008) bapak andre akan terus menerus mencatat cost maupun expense untuk menyelesaikan pesanan yang pembayarannya sudah dibukukan pada Laporan Laba/Rugi periode sebelumnya. Sehingga pada penutupan buku bulan Maret 2008 bapak andre akan membukukan Rugi (Lost) yang setidak-tidaknya sama dengan cost dan expense yang timbul selama periode tersebut. Jika ditampilkan dalam grafik, maka performance trend yang dihasilkan akan kelihatan aneh alias tidak wajar. Terjadi fluktuasi yang drastis dari periode Februari ke periode Maret 2008.
Bagaimana dan kapan melakukan pengakuan yang lebih sesuai agar trend laba rugi wajar?
Tips:
Setiap transaksi pendapatan yang belum menimbulkan biaya dicatat di rekening yang ada di Neraca.
Dalam contoh kasus bapak Andre di atas sebaiknya dicatat (perhatikan jadwal pengiriman dan rencana pembayaran) di atas.
Pada tanggal 25 Feb 2008 (saat menerima pembayaran pertama) di catat:
[Debit]. Kas = Rp 30,000,000,-
[Credit]. Pendapatan diterima dimuka = Rp 30,000,000
Pada tanggal 1 Maret 2008 (saat pengiriman barang pertama) di catat:
[Debit]. Harga Pokok Penjualan
[Credit]. Persediaan
[Debit]. Pendapatan Diterima di Muka = Rp 15,000,000
[Credit]. Penjualan = Rp 15,000,000
Catatan: Penjualan mulai diakui pada saat barang dikirimkan (diserahkan), DAN… atas penjualan yang terjadi SUDAH dapat disandingkan dengan cost yang timbul di periode yang sama, yaitu Harga Pokok Penjualan. Perhatikan Pendapatan diterima Di Muka, dengan jurnal pada tanggal 01 Maret 2008, maka saldo Pendapatan Diterima di Muka tinggal sebesar Rp 15,000,000 saja.
Pada tanggal 15 Maret 2008 (saat pengiriman barang ke-2) dicatat:
[Debit]. Harga Pokok Penjualan
[Credit]. Persediaan
[Debit]. Pendapatan Diterima di Muka = Rp 15,000,000
[Credit]. Penjualan = Rp 15,000,000
Catatan: Lagi-lagi penjualan dicatat sebesar Rp 15,000,000 dengan mendebit rekening Pendapatan Diterima di Muka, sehingga total penjualan telah mencapai Rp 30,000,000,- dan saldo rekening Pendapatan Diterima di Muka menjadi 0 (nol).
Pada tanggal 30 Maret 2008 (saat pengiriman terakhir dilakukan), pembayaran belum diterima, sehingga dicatat:
[Debit]. Harga Pokok Penjualan
[Credit]. Persediaan
[Debit]. Piutang = Rp 20,000,000
[Credit]. Penjualan = Rp 20,000,000
Pada tanggal 01 April 2008 (saat pembayaran diterima) dicatat:
[Debit]. Kas = Rp 20,000,000,-
[Credit]. Piutang = Rp 20,000,000,-
Catatan: Pada pengiriman barang yang ketiga (terakhir) ini, barang diserahkan, dan penjualan dapat dilawankan dengan Harga Pokok Penjualannya, sehingga wajar jika diakui sebagai penjualan. Jikapun kas belum diterima, toh bisa mendebit rekening Piutang.
Kesimpulan
Jika kita perhatikan jurnal-jurnal diatas, dapat kita lihat bahwa pada setiap pengakuan Penjualan selalu bersandingan dengan pengakuan Harga Pokok Penjualan (cost factor) dilegalisasi dengan berpindahnya fisik barang yang tercermin dalam rekening persediaan yang saldonya juga semakin berkurang (berada di sisi kredit). Inilah “Essential of The Matching Principle” didalam akuntansi.
Apakah ketidak-sesuaian pencatatan yang dilakukan oleh bapak Andre diawal transaksi (saat penerimaan pembayaran pertama) perlu dibuatkan adjustment entry?
Jawaban saya : "It depends on………"
Tergantung, jika pada pengiriman barang pertama dan kedua bapak Andre hanya mengakui Harga Pokok Penjualan dengan mengkredit rekening Persediaan SAJA, tanpa mencatat penjualan lagi. Maka adjustment entry rasanya TIDAK MUTLAK DIPERLUKAN.
Mengapa ?
Bapak Andre hanya terlalu dini mengakui penjualan, yang dalam akuntansi diistilahkan dengan “EARLY REVENUE RECOGNITION”, Early Revenue Recognition MASIH tergolong “MIS-STATEMENT”, belum termasuk “MATERIAL ISSUE”. Toh terjadi masih dalam tahun buku yang sama, dimana Revenue Overstatement yang terjadi dibulan Februari akan terimbangi oleh Cost Overstatement di bulan Maret. Hanya saja trend-nya menjadi tidak wajar. Lain cerita jika kasusnya "PREMATURE REVENUE RECOGNITION" yaitu pengakuan pendapatan atas suatu potensi pendapatan atau yang masih berupa commitment, maka itu akan tergolong "Material Issue". Hanya saja kebiasaan pencatatan seperti yang dilakukan oleh bapak Andre pada contoh kasus ini, sebaiknya dihindari, karena akan merepotkan jika terjadi di akhir tahun buku.
Minggu, 30 Maret 2008
Laba Rugi Komersial dan Fiskal
Dalam Pelaporan Keuangan Perusahaan, khususnya “Laporan Laba Rugi”, kita mengenal adanya LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL dan LAPORAN LABA RUGI FISKAL. Mengapa ada Laporan Laba Rugi Komersial dan Laporan Laba Rugi Fiskal? Apa saja perbedaannya? Bagaimana caranya membuat Laporan Laba Rugi Fiskal? Bagaimana jika tidak dibedakan? Mungkinkah kedua laporan laba rugi ini dijadikan satu? Bagaimana caranya? Akan kita bahas di artikel ini sebentar lagi.
Artikel ini saya dedikasikan bagi mereka yang “belum sepenuhnya” memahami dan belum bisa membuat laporan laba rugi fiskal. Mudah-mudahan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan detail. Seperti biasa saya akan memberikan langkah-langkah pembuatannya. Termasuk TRICK “Bagaimana menyatukan Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal ke dalam satu lembar laporan saja”.
Untuk rekan-rekan yang SPT Tahunannya sudah lolos saya ucapkan “Congratulation!”. Sedangkan yang masih berjuang memasukkannya saya ucapkan “Good luck!”. Dan bagi yang masih bingung membuat SPT PPh Badan, mungkin ada baiknya membaca artikel ini :-). Meskipun yang dibahas bukan cara mengisi SPT PPh Badan, tetapi... adalah tidak mungkin bagi anda untuk membuat SPT PPh Badan jika anda belum memahami apa itu Laporan Laba Rugi Fiskal, karena data source SPT PPh Badan adalah Laporan Laba Rugi Fiskal.
Kiranya saya tidak perlu lagi memberikan penjelasan mengenai apa itu Laporan Laba Rugi. Jika kebetulan ada yang belum tahu, saya encourage anda untuk membaca kembali buku “Pengantar Akuntansi Keuangan” atau “Dasar-dasar Akuntansi Keuangan”.
Mengapa Ada Laporan Rugi Laba Komersial dan Fiskal?
Karena adanya perbedaan pengakuan atas pendapatan maupun biaya menurut perusahaan (selaku wajib pajak) dengan pihak Ditjen Pajak (selaku fiskus yang mewakili negara). Sederhananya: ada pendapatan maupun biaya yang diakui sebagai pendapatan maupun biaya oleh perusahaan tetapi tidak diakui oleh Ditjend Pajak.
Mengapa berbeda dan apa saja perbedaaanya?
Bagi perusahaan: semua pemasukan adalah pendapatan yang akan menambah laba kena pajak , dan semua pengeluaran adalah beban yang akan mengurangi laba kena pajak. Bagi Ditjend Pajak: tidak semua pemasukan adalah faktor penambah laba kena pajak, ada beberapa jenis pendapatan yang bukan merupakan faktor penambah laba kena pajak karena pendapatan tersebut sudah dikenakan pajak bersifat final, dan tidak semua pengeluaran adalah faktor pengurang laba kena pajak karena ada beberapa jenis pengeluaran yang sesungguhnya bukan merupakan bagian dari kegiatan perusahaan. Di dalam Akuntansi Perpajakan perbedaan ini disebut dengan BEDA TETAP.
Perbedaan lainnya adalah perebedaan yang diakibatkan karena bedanya SAAT PENGAKUAN (waktu pengakuan) baik itu terhadap pendapatan maupun beban (pendapatan/beban tangguhan), juga akibat perbedaan beban penyusutan dimana pihak Ditjend Pajak menggunakan metode penyusutan GARIS LURUS (Straight Line Method) sementara perusahaan mungkin menggunakan metode penyusutan yang lain, yang oleh karenanya mengakibatkan adanya perbedaan alokasi beban penyusutan. Prakiraan Umur ekonomis atas aktiva tetap juga turut memberi kontribusi atas perbedaan tersebut. Dalam Akuntansi Perpajakan ini disebut dengan BEDA WAKTU.
Perbedaan-perbedaan tersebut memerlukan penyesuaian-penyesuaian agar JUMLAH PAJAK PENGHASILAN BADAN TERHUTANG antara yang dihitung oleh perusahaan dengan menurut Ditjend Pajak bisa sama. Penyesuaian tersebutlah yang dikenal dengan istilah KOREKSI FISKAL.
Ada 2 (dua) macam penyesuaian fiskal, yaitu:
Penyesuaian Fiskal Positif: adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan terhutangnya juga akan meningkat.
Penyesuaian Fiskal Negatif: adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak.
Berikut ini adalah tabel rincian jenis-jenis penyesuaian tersebut:

Bagaimana Cara Membuat Laporan Laba Rugi Fiskal?
Saya akan coba construct satu kasus:
Buku Besar PT. ABC nampak seperti dibawah:

Jika kita susun menjadi Laporan Laba Rugi, kita akan menghasilkan laporan seperti dibawah ini:

Apakah Laporan Laba Rugi diatas benar?
Laporan Komersial iya benar, hanya saja “Pajak Penghasilan” nya belum benar.Bukankah seharusnya ada penyesuaian-penyesuaian?.
Okay, kita bandingkan dengan table rincian penyesuaian fiskal positif dan negative di atas. Menurut table, ada beberapa yang harus disesuaikan, yaitu:
“Bunga Jasa Giro” telah dikenakan pajak oleh pihak bank, maka ini dimasukkan sebagai “Pendapatan dikenakan Pajak Final”, sehingga ini tidak seharunya dikenakan pajak lagi. Kita jadikan faktor pengurang Laba Kena Pajak.
“Pengambilan Oleh Direktur” ini adalah bukan beban perusahaan. Direktur hanya boleh menerima Gaji dan Dividen saja. Maka kita masukkan ke dalam koreksi fiskal positif (faktor penambah laba kena pajak).
“Makan Untuk Pegawai” ini adalah bentuk kenikmatan (natura) yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai, ini tidak diakui sebagai beban perusahaan. Catatan : saya pribadi kurang setuju dengan anggapan ini, karena pemberian incentive berupa makan, minum atau bentuk kenikmatan lainnya kepada pegawai adalah salah satu usaha perusahaan untuk merangsang semangat kerja pegawai, sangat bisa dihubungkan dengan potensi peningkatan revenue perusahaan. Seharunya tidak alasan untuk menggap ini tidak ada hubungannya dengan aktivitas perusahaan, jelas-jelas ini beban (biaya) yang bisa di set off dengan revenue. Saya pernah argue dengan pihak kantor pajak tentang hal ini. Lebih detailnya saya akan bahas di artikel lain.
“Sumbangan” ini bukan beban perusahaan, tidak bisa dihubungkan dengan revenue. Sehingga kita masukkan ini ke dalam kelompok koreksi fiskal positif.
Saya tidak menemukan koreksi fiskal negative dalam contoh kasus ini.sehingga nanti koreksi fiskal negatifnya akan 0 (nol).
Setelah unsur koreksi fiskal kita masukkan, maka Laporan Laba Rugi akan menjadi seperti dibawah ini:

Apakah kali ini sudah benar?
Laporan Fiskal Iya benar. Bagaimana dengan laporan komersialnya?, apakah laba setelah pajak di atas bisa kita masukkan ke dalam neraca (Laba Tahun Berjalan)?.
Coba pikirkan baik-baik……………………………………………………………………
………………………………….. yakin?.
NO…. big no!
Bukankah di neraca nanti laba ini akan di off set dengan mutasi rekening-rekening di kelompok asset (aktiva)?. Sudah ada clue?.....belum?
Okay, diakui atau tidak diakui semua koreksi fiskal tersebut (bunga jasa giro, pengambilan direktur, makan untuk pegawai, sumbangan) adalah berpengaruh langsung terhadap posisi (saldo) kas. Jika semua itu tidak diakui, sementara di sisi lainnya, laba kita paksakan masuk ke neraca, maka sudah pasti NERACA TIDAK AKAN BALANCE!.
Lalu, bagaimana?
Kita harus kembalikan semua koreksi tersebut.
Dikembalikan?, berarti labanya menjadi salah lagi?.
Maksud saya, semua unsure tadi tetap kita koreksi, setelah kita peroleh “laba fiskal setelah pajak”, baru kita kembalikan semua koreksi fiskal tersbut.
Caranya?
Perhatikan Laporan Laba Rugi dibawah ini:

Bahkan kita berhasil memperoleh Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal dalam satu lembar laporan saja, anda tidak perlu lagi membuat laporan laba rugi dalam 2 (versi) :-)
Sekarang Laba setelah pajaknya sudah bisa di masukkan ke dalam neraca. Dan pasti balance. Guaranteed! :-)
Selamat mencoba!
Artikel ini saya dedikasikan bagi mereka yang “belum sepenuhnya” memahami dan belum bisa membuat laporan laba rugi fiskal. Mudah-mudahan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan detail. Seperti biasa saya akan memberikan langkah-langkah pembuatannya. Termasuk TRICK “Bagaimana menyatukan Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal ke dalam satu lembar laporan saja”.
Untuk rekan-rekan yang SPT Tahunannya sudah lolos saya ucapkan “Congratulation!”. Sedangkan yang masih berjuang memasukkannya saya ucapkan “Good luck!”. Dan bagi yang masih bingung membuat SPT PPh Badan, mungkin ada baiknya membaca artikel ini :-). Meskipun yang dibahas bukan cara mengisi SPT PPh Badan, tetapi... adalah tidak mungkin bagi anda untuk membuat SPT PPh Badan jika anda belum memahami apa itu Laporan Laba Rugi Fiskal, karena data source SPT PPh Badan adalah Laporan Laba Rugi Fiskal.
Kiranya saya tidak perlu lagi memberikan penjelasan mengenai apa itu Laporan Laba Rugi. Jika kebetulan ada yang belum tahu, saya encourage anda untuk membaca kembali buku “Pengantar Akuntansi Keuangan” atau “Dasar-dasar Akuntansi Keuangan”.
Mengapa Ada Laporan Rugi Laba Komersial dan Fiskal?
Karena adanya perbedaan pengakuan atas pendapatan maupun biaya menurut perusahaan (selaku wajib pajak) dengan pihak Ditjen Pajak (selaku fiskus yang mewakili negara). Sederhananya: ada pendapatan maupun biaya yang diakui sebagai pendapatan maupun biaya oleh perusahaan tetapi tidak diakui oleh Ditjend Pajak.
Mengapa berbeda dan apa saja perbedaaanya?
Bagi perusahaan: semua pemasukan adalah pendapatan yang akan menambah laba kena pajak , dan semua pengeluaran adalah beban yang akan mengurangi laba kena pajak. Bagi Ditjend Pajak: tidak semua pemasukan adalah faktor penambah laba kena pajak, ada beberapa jenis pendapatan yang bukan merupakan faktor penambah laba kena pajak karena pendapatan tersebut sudah dikenakan pajak bersifat final, dan tidak semua pengeluaran adalah faktor pengurang laba kena pajak karena ada beberapa jenis pengeluaran yang sesungguhnya bukan merupakan bagian dari kegiatan perusahaan. Di dalam Akuntansi Perpajakan perbedaan ini disebut dengan BEDA TETAP.
Perbedaan lainnya adalah perebedaan yang diakibatkan karena bedanya SAAT PENGAKUAN (waktu pengakuan) baik itu terhadap pendapatan maupun beban (pendapatan/beban tangguhan), juga akibat perbedaan beban penyusutan dimana pihak Ditjend Pajak menggunakan metode penyusutan GARIS LURUS (Straight Line Method) sementara perusahaan mungkin menggunakan metode penyusutan yang lain, yang oleh karenanya mengakibatkan adanya perbedaan alokasi beban penyusutan. Prakiraan Umur ekonomis atas aktiva tetap juga turut memberi kontribusi atas perbedaan tersebut. Dalam Akuntansi Perpajakan ini disebut dengan BEDA WAKTU.
Perbedaan-perbedaan tersebut memerlukan penyesuaian-penyesuaian agar JUMLAH PAJAK PENGHASILAN BADAN TERHUTANG antara yang dihitung oleh perusahaan dengan menurut Ditjend Pajak bisa sama. Penyesuaian tersebutlah yang dikenal dengan istilah KOREKSI FISKAL.
Ada 2 (dua) macam penyesuaian fiskal, yaitu:
Penyesuaian Fiskal Positif: adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan terhutangnya juga akan meningkat.
Penyesuaian Fiskal Negatif: adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak.
Berikut ini adalah tabel rincian jenis-jenis penyesuaian tersebut:
Bagaimana Cara Membuat Laporan Laba Rugi Fiskal?
Saya akan coba construct satu kasus:
Buku Besar PT. ABC nampak seperti dibawah:
Jika kita susun menjadi Laporan Laba Rugi, kita akan menghasilkan laporan seperti dibawah ini:
Apakah Laporan Laba Rugi diatas benar?
Laporan Komersial iya benar, hanya saja “Pajak Penghasilan” nya belum benar.Bukankah seharusnya ada penyesuaian-penyesuaian?.
Okay, kita bandingkan dengan table rincian penyesuaian fiskal positif dan negative di atas. Menurut table, ada beberapa yang harus disesuaikan, yaitu:
“Bunga Jasa Giro” telah dikenakan pajak oleh pihak bank, maka ini dimasukkan sebagai “Pendapatan dikenakan Pajak Final”, sehingga ini tidak seharunya dikenakan pajak lagi. Kita jadikan faktor pengurang Laba Kena Pajak.
“Pengambilan Oleh Direktur” ini adalah bukan beban perusahaan. Direktur hanya boleh menerima Gaji dan Dividen saja. Maka kita masukkan ke dalam koreksi fiskal positif (faktor penambah laba kena pajak).
“Makan Untuk Pegawai” ini adalah bentuk kenikmatan (natura) yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai, ini tidak diakui sebagai beban perusahaan. Catatan : saya pribadi kurang setuju dengan anggapan ini, karena pemberian incentive berupa makan, minum atau bentuk kenikmatan lainnya kepada pegawai adalah salah satu usaha perusahaan untuk merangsang semangat kerja pegawai, sangat bisa dihubungkan dengan potensi peningkatan revenue perusahaan. Seharunya tidak alasan untuk menggap ini tidak ada hubungannya dengan aktivitas perusahaan, jelas-jelas ini beban (biaya) yang bisa di set off dengan revenue. Saya pernah argue dengan pihak kantor pajak tentang hal ini. Lebih detailnya saya akan bahas di artikel lain.
“Sumbangan” ini bukan beban perusahaan, tidak bisa dihubungkan dengan revenue. Sehingga kita masukkan ini ke dalam kelompok koreksi fiskal positif.
Saya tidak menemukan koreksi fiskal negative dalam contoh kasus ini.sehingga nanti koreksi fiskal negatifnya akan 0 (nol).
Setelah unsur koreksi fiskal kita masukkan, maka Laporan Laba Rugi akan menjadi seperti dibawah ini:
Apakah kali ini sudah benar?
Laporan Fiskal Iya benar. Bagaimana dengan laporan komersialnya?, apakah laba setelah pajak di atas bisa kita masukkan ke dalam neraca (Laba Tahun Berjalan)?.
Coba pikirkan baik-baik……………………………………………………………………
………………………………….. yakin?.
NO…. big no!
Bukankah di neraca nanti laba ini akan di off set dengan mutasi rekening-rekening di kelompok asset (aktiva)?. Sudah ada clue?.....belum?
Okay, diakui atau tidak diakui semua koreksi fiskal tersebut (bunga jasa giro, pengambilan direktur, makan untuk pegawai, sumbangan) adalah berpengaruh langsung terhadap posisi (saldo) kas. Jika semua itu tidak diakui, sementara di sisi lainnya, laba kita paksakan masuk ke neraca, maka sudah pasti NERACA TIDAK AKAN BALANCE!.
Lalu, bagaimana?
Kita harus kembalikan semua koreksi tersebut.
Dikembalikan?, berarti labanya menjadi salah lagi?.
Maksud saya, semua unsure tadi tetap kita koreksi, setelah kita peroleh “laba fiskal setelah pajak”, baru kita kembalikan semua koreksi fiskal tersbut.
Caranya?
Perhatikan Laporan Laba Rugi dibawah ini:

Bahkan kita berhasil memperoleh Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal dalam satu lembar laporan saja, anda tidak perlu lagi membuat laporan laba rugi dalam 2 (versi) :-)
Sekarang Laba setelah pajaknya sudah bisa di masukkan ke dalam neraca. Dan pasti balance. Guaranteed! :-)
Selamat mencoba!
Kamis, 27 Maret 2008
Tips Membuat Proses Penyetoran SPT PPh Pasal 29 menjadi lancar.
[-]. Sebelum berangkat membawa SPT ke KPP, jangan lupa periksa kembali, pastikan semua kelengkapan SPT (i.e.: Identitas WP, Lampiran-lampiran), termasuk SSP PPh pasal 29 Lembar ke-3 sudah ada di dalam folder.
[-]. Jangan Lupa stempel perusahaan dan tanda tangan yang authorized disetiap lembaran yang diminta.
[-]. Pastikan semua lembaran sudah terisi.
[-]. Jangan sekali-sekali mengirimkan kurir untuk setor SPT Tahunan, karena sebelum proses pelaporan di counter, maap anda akan discreening dahulu, diteliti dan diperiksa, untuk kemudian diparaf jika dianggap sudah benar oleh petugas.
[-]. Percaya atau tidak, timing penyetoran significantly berpengaruh. Jika anda berangkat sebelum “Lunch Break”, sebaiknya cari tempat relax sebentar untuk makan siang. Setorkanlah SPT Tahunan anda setelah “Lunch Break”. Mengapa? “Morning Stress” kurang baik, anda masih membawa stress, petugas pajak yang akan screening map anda pun masih membawa morning stress.
[-]. Pada saat map anda diperiksa bersikaplah santai tetapi serius, maksud saya jangan tegang tetapi juga jangan kelihatan chu-lun tentunya.
[-]. Jika ada pertanyaan atau koreksi dari petugas “jangan arguing”, sekalipun anda sangat mengerti perpajakan, veteran pajak sekalipun. Kedepankan professional dan respecting each other. Jika ditemukan kesalahan, bersikaplah meminta petunjuk, dengan bertanya yang sederhana-sederhana saja. Dengan kata lain “Jangan Sok nge-jago” sekalipun yang memeriksa maap anda kelihatan masih sangat muda sementara mungkin anda sudah lebih senior.
[-]. Scenario terburuk, jika terpaksa anda harus kembali, jangan segan-segan untuk kembali dan melakukan koreksi, lebih baik setorkan setelah dikoreksi.
Semoga proses penyetoran SPT anda lancar dan sukses.
[-]. Jangan Lupa stempel perusahaan dan tanda tangan yang authorized disetiap lembaran yang diminta.
[-]. Pastikan semua lembaran sudah terisi.
[-]. Jangan sekali-sekali mengirimkan kurir untuk setor SPT Tahunan, karena sebelum proses pelaporan di counter, maap anda akan discreening dahulu, diteliti dan diperiksa, untuk kemudian diparaf jika dianggap sudah benar oleh petugas.
[-]. Percaya atau tidak, timing penyetoran significantly berpengaruh. Jika anda berangkat sebelum “Lunch Break”, sebaiknya cari tempat relax sebentar untuk makan siang. Setorkanlah SPT Tahunan anda setelah “Lunch Break”. Mengapa? “Morning Stress” kurang baik, anda masih membawa stress, petugas pajak yang akan screening map anda pun masih membawa morning stress.
[-]. Pada saat map anda diperiksa bersikaplah santai tetapi serius, maksud saya jangan tegang tetapi juga jangan kelihatan chu-lun tentunya.
[-]. Jika ada pertanyaan atau koreksi dari petugas “jangan arguing”, sekalipun anda sangat mengerti perpajakan, veteran pajak sekalipun. Kedepankan professional dan respecting each other. Jika ditemukan kesalahan, bersikaplah meminta petunjuk, dengan bertanya yang sederhana-sederhana saja. Dengan kata lain “Jangan Sok nge-jago” sekalipun yang memeriksa maap anda kelihatan masih sangat muda sementara mungkin anda sudah lebih senior.
[-]. Scenario terburuk, jika terpaksa anda harus kembali, jangan segan-segan untuk kembali dan melakukan koreksi, lebih baik setorkan setelah dikoreksi.
Semoga proses penyetoran SPT anda lancar dan sukses.
COGS, PPn & PPh Pasal 22 Import
Artikel ini akan membahas mengenai : Penentuan COGS, hubungannya dengan PPn Import, PPh Pasal 22 Import, beserta pengkreditan kedua jenis pajak tersebut. Diangkat dari kasus yang disampaikan oleh saudara Ydy di Jakarta. Akan dibahas step by step dengan screen shoot – screen shoot dan konstruksi: Proses Penjurnalan, Buku Besar, Inventory Card, hingga Profit & Lost Statement. Saya mengusahakannya sesederhana dan sesingkat mungkin agar mudah dipahami dan diikuti oleh siapapun (yang tidak pernah menangani kasus import sekalipun), tentu saja tanpa mengabaikan detail dan konsep dasar dan logika-logikanya. Dan seperti biasa saya akan sertai catatan-catatan yang saya anggap penting.
Artikel kasus ini saya dedikasikan untuk semua rekan-rekan dibagian accounting, keuangan dan perpajakan yang sedang mengejar deadline SPT Tahun Takwim 2007 yang sudah harus disetor paling lambat tanggal 20 Maret, dan laporan paling lambat tanggal 25 Maret ini, tinggal beberapa hari saja. Saya ada tips khusus diakhir artikel nanti :-)
Kita langsung ke kasusnya:
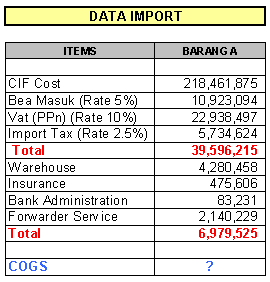
Data Import
Pada tanggal 01 February 2008, PT. Royal Bali Cemerlang mengimport barang dagangan dari Canada sebanyak 4700 unit dengan data-data (setelah di-convert ke Rupiah) sebagai berikut:
Catatan: Perhatikan data import diatas, ada beberapa element import biasa timbul. Sayang sekali data yang diberikan tidak sampai pada data penjualannya. Tetapi seperti saya sampaikan diawal, jangan khawatir, saya akan construct hingga menjadi “Profit & Lost Statement” bahkan hingga penjurnalan kredit PPn & PPh Pasal 22 Import-nya. Kerja accounting tidak boleh setengah-setengah bukan?
Pengakuan Atas Element Import
Adapun element-element pengeluaran yang common occurred on import process:
[-]. CIF : It is stand for “Cost, Insurance & Freight”. Ini adalah element utama. Nilai Barang yang kita Import. Kebetulan pada kasus ini data yang tersedia adalah CIF, sehingga tidak muncul element freight (biaya kirim). Karena CIF Cost adalah mewakili nilai barang yang kita import maka nantinya akan kita akui sebagai “Inventory”.
[-]. Bea Masuk (Import Duty): adalah pengeluaran atas bea masuk yang kenakan oleh Dit Jend Bea Cukai (DJBC). Tariff nya bervariasi tergantung jenis barang yang diimport, tetapi dalam kasus ini kita sudah ketahui tariffnya 5% (sangat rendah ya?)
[-]. PPn Import (VAT): adalah Pajak Pertambahan nilai atas Import yang tariffnya 10%.
[-]. PPh Pasal 22 Import: adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Import, yang dalam kasus ini tariffnya 2.5% (juga sangat rendah ya?)
[-]. Warehousing: adalah pengeluaran atas sewa gudang (mungkin barang sempat menginap di pelabuhan sehingga kena demurrage charge).
[-]. Insurance: saya sedikit ragu, padahal nilai barang sudah CIF, mengapa muncul insurance lagi? Anyway, kita masukkan sajalah.
[-]. Bank Charge: Bank charge ini adalah khusus charge yang dikenakan oleh bank atas proses import ini, bukan dari lalulintas pembayaran umum yang on daily bases, sehingga bank charge ini merupakan element import juga.
[-]. Forwarding Services: Adalah cost yang timbul akibat penggunaan jasa Forwarder yang bertindak sebagai broker da;lam proses import ini (ground handling, custom clearance, dan lain sebagainya).
Konsep dasarnya: semua pengeluaran sehubungan dengan Import (yang mebawa barang hingga tiba di gudang Importer) diakui sebagai Element COGS. Pengakuan atas element-element import ini kita jurnal seperti dibawah ini :

Catatan : Perhatikan jurnal diatas: CIF Cost kita akui sebagai Inventory
Penjualan
Pada tanggal 15 February PT, Royal Bali Cemerlang menjual barang dagangannya sebanyak 2000 unit, dengan unit price Rp 76,269,- secara kredit, kita akui penjualan tersebut dengan jurnal:

Catatan: dalam penjualan barang dagangan, ada 2 jurnal yang harus kita masukkan, yaitu untuk mengakui pengeleuaran barang (pengurangan inventory) dan jurnal satunya lagi untuk mengakui penjualannya itu sendiri. Jangan lupa “Penjualaan dalam negeri” adalah terhutang PPn dengan tariff 10%, yang langsung diakui saat pengakuan penjualan. Diakui sebagai utang karena PPn baru disetorkan ke kas negara (melalui bank persepsi) pada tanggal 10 bulan berikutnya.
Pada tanggal 27 February lagi-lagi PT. Royal Bali Cemerlang berhasil menjual barang dagangannya sebanyak 1500 unit dengan unit price yang sama dan masih memakai sistem credit dalam pembayarannya. Sehingga lagi sekali kita jurnal:

Buku Besar dan Inventory Card
Tanggal sudah menunjukkan 29 February 2008, saatnya melakukan “Monthly Closing Book”.
Pertama kita bikin buku besarnya dahulu, dengan jurnal pengakuan import dan penjualan-penjualan diatas dan diasumsikan saldo awal semua rekening adalah 0 (nol), buku besarnya akan menjadi seperti dibawah ini:

Catatan: Perhatikan rekening-rekening pada buku besar di atas dan akan kemana masing-masing rekening tersebut dimasukkan ada yang ke Balance Sheet dan ada yang ke Profit & Lost Statement.
Dan pada “Inventory Card” yang kita di Indonesia biasa menyebutnya “Kartu Stock” (saya sedikit berhati-hati meamaki istilah stock, karena takut bingung dengan saham), dengan asumsi Saldo awal inventory adalah nol, ada pembelian dan penjualan, maka inventory card akan menjadi (tentunya di pastikan terlebih dahulu dengan physical count):

Catatan : Perhatikan rekenening “Inventory” pada buku besar diatas, saldo akhir sama-sama menunjukkan angka Rp 55,777,500,- artinya proses jurnal sudah in synchronized dengan Inventory Card. Great!. Oh ya, diingat-ingat ya angka ini. Lets go to the next step….
Profit & Lost Statement
Ok, so kita sudah punya “Buku Besar” dan “Inventory Card”. Sekarang waktunya kita construct “Profit & Lost Statament”. Session yang paling saya sukai :-)
Profit & Lost Statement pada umumnya terdiri dari :
Revenue, diambil dari rekening Sales pada buku besar, seharunya ada elemen “Other Revenues” i.e.: Bunga Jasa Giro, dan pendapatan lainnya, tetapi pada kasus ini, data-data tersebut tidak tersedia. Maka diambil dari sales saja.
Cost Of Good Sold (Harga Pokok Penjualan), dipecah lagi menjadi : Inventory, Raw Material, Direct Labor Cost, Overhead Cost. Tetapi pada kasus ini, Direct Labor Cost dan Raw Metrial tidak tersedia, sebagai gantinya hanya muncul muncul semua element expenditure sehubungan dengan Import yang sesungguhnya merupakan “Overhead Cost” yang saya munculkan seperti aslinya, agar mudah dipahami.
Gross Profit, didapat dengan formula : Revenue [minus] COGS.
Expenses, adalah biaya-biaya yang muncul sehubungan operasional perusahaan yang tidak dipengaruhi oleh output (produktifitas) perusahaan. Seharusnya ada elemen depreciation/amortization expenses, akan tetapi pada kasus ini saya tidak munculkan agar lebih sederhana.
Earning Before Tax, diperoleh dengan formula: Gross Profit [minus] Expenses
Setelah semua elemen diatas seharusnya ada : Corporate Income Tax (PPh Badan), Earning After Tax (Profit Earning). Tetapi karena kasus ini focus pada penentuan “COGS” saja, maka saya tidak akan bahas di posting ini (kita bahas di postingan yang lain).
Setelah saya construct, semua angka saya masukkan, maka Profit & Lost statement menjadi seperti dibawah ini:
Catatan :

Perhatikan pada element B (COGS/HPP), pada proses import, elemen-elemen apa saja yang dimasukkan. Dan khusus untuk “Inventory” misi kita adalah mencari berapa besarnya “Persediaan Barang Terpakai” dan telah kita peroleh sebesar Rp 162,684,375,- yang didapat dengan formula : Saldo Awal [plus] Pembelian [minus] Persediaan akhir. Persediaan akhir kita peroleh dari buku besar atau inventory Card.
Penerimaan Pelunasan Piutang
Pada tanggal 05 Maret 2008, PT. Royal Bali Cemerlang menerima pelunasan piutang untuk kesemua penjualan yang terjadi pada bulan February, maka dijurnal:

Catatan: Perhatikan catatan dibawah jurnal
Pembayaran PPn
Seperti sudah disampaikan sebelumnya bahwa PPn atas penjualan dalam negeri disetorkan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, maka pada tanggal 09 Maret 2008 dilakukan penyetoran PPn ke kas negara melalaui “Bank Persepsi”, dan atas setoran tersebut dijurnal:

Catatan Penting:
Pada jurnal diatas, pada sisi debit dimasukkan PPn Terhutang, ini akan membuat rekening PPn Terhutang pada Neraca 29 February akan menjadi 0 (nol). Sedangkan pada sisi kredit Cash yang dibayarkan hanya sebesar Rp 3,755,614,- bukan sebesar PPn terhutang, karena PPn Import kita kreditkan saat ini. Ya, kita kreditkan!.
Maka bisa saya katakan disini bahwa: Jika mekanisme proses perhitungan dan pelaporan PPn dilakukan dengan benar, maka prinsip dasar PPn dimana “PPn adalah Pajak Pertambahan Nilai yang artinya, Pajak yang dibayarkan hanyalah sebesar 10% [kali] value added yang berhasil dicreate oleh perusahaan saja”, bukan sebesar 10% [kali] Penjualan Kotor. Pada pembelian bukan import pun ada PPn masukan bukan?. Yang harus diperhatikan disini adalah selalu mintalah Faktur Pajak Masukan anda kepada supplier yang mengenakan PPn atas pembelian raw metrial maupun pembelian lainnya.
PPh Pasal 22 Import
Menjelang pembuatan SPT PPh Badan, dibuatkan jurnal:

Update: 13-Maret-2008
Pada jurnal di atas, seharusnya: [Debit]. PPh Pasal 29 (terhutang), bukan PPh Pasal 22.
Sorry about that.
Catatan: PPh Pasal 22 Import akan menjadi faktor pengurang PPh Pasal 29 nantinya.
Besar harapan saya, artikel ini bisa dipahami sehingga bisa memberikan manfaat bagi pembaca.
Semoga proses penyetoran SPT anda lancar dan sukses.
Artikel kasus ini saya dedikasikan untuk semua rekan-rekan dibagian accounting, keuangan dan perpajakan yang sedang mengejar deadline SPT Tahun Takwim 2007 yang sudah harus disetor paling lambat tanggal 20 Maret, dan laporan paling lambat tanggal 25 Maret ini, tinggal beberapa hari saja. Saya ada tips khusus diakhir artikel nanti :-)
Kita langsung ke kasusnya:
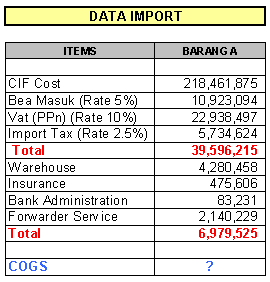
Data Import
Pada tanggal 01 February 2008, PT. Royal Bali Cemerlang mengimport barang dagangan dari Canada sebanyak 4700 unit dengan data-data (setelah di-convert ke Rupiah) sebagai berikut:
Catatan: Perhatikan data import diatas, ada beberapa element import biasa timbul. Sayang sekali data yang diberikan tidak sampai pada data penjualannya. Tetapi seperti saya sampaikan diawal, jangan khawatir, saya akan construct hingga menjadi “Profit & Lost Statement” bahkan hingga penjurnalan kredit PPn & PPh Pasal 22 Import-nya. Kerja accounting tidak boleh setengah-setengah bukan?
Pengakuan Atas Element Import
Adapun element-element pengeluaran yang common occurred on import process:
[-]. CIF : It is stand for “Cost, Insurance & Freight”. Ini adalah element utama. Nilai Barang yang kita Import. Kebetulan pada kasus ini data yang tersedia adalah CIF, sehingga tidak muncul element freight (biaya kirim). Karena CIF Cost adalah mewakili nilai barang yang kita import maka nantinya akan kita akui sebagai “Inventory”.
[-]. Bea Masuk (Import Duty): adalah pengeluaran atas bea masuk yang kenakan oleh Dit Jend Bea Cukai (DJBC). Tariff nya bervariasi tergantung jenis barang yang diimport, tetapi dalam kasus ini kita sudah ketahui tariffnya 5% (sangat rendah ya?)
[-]. PPn Import (VAT): adalah Pajak Pertambahan nilai atas Import yang tariffnya 10%.
[-]. PPh Pasal 22 Import: adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Import, yang dalam kasus ini tariffnya 2.5% (juga sangat rendah ya?)
[-]. Warehousing: adalah pengeluaran atas sewa gudang (mungkin barang sempat menginap di pelabuhan sehingga kena demurrage charge).
[-]. Insurance: saya sedikit ragu, padahal nilai barang sudah CIF, mengapa muncul insurance lagi? Anyway, kita masukkan sajalah.
[-]. Bank Charge: Bank charge ini adalah khusus charge yang dikenakan oleh bank atas proses import ini, bukan dari lalulintas pembayaran umum yang on daily bases, sehingga bank charge ini merupakan element import juga.
[-]. Forwarding Services: Adalah cost yang timbul akibat penggunaan jasa Forwarder yang bertindak sebagai broker da;lam proses import ini (ground handling, custom clearance, dan lain sebagainya).
Konsep dasarnya: semua pengeluaran sehubungan dengan Import (yang mebawa barang hingga tiba di gudang Importer) diakui sebagai Element COGS. Pengakuan atas element-element import ini kita jurnal seperti dibawah ini :

Catatan : Perhatikan jurnal diatas: CIF Cost kita akui sebagai Inventory
Penjualan
Pada tanggal 15 February PT, Royal Bali Cemerlang menjual barang dagangannya sebanyak 2000 unit, dengan unit price Rp 76,269,- secara kredit, kita akui penjualan tersebut dengan jurnal:

Catatan: dalam penjualan barang dagangan, ada 2 jurnal yang harus kita masukkan, yaitu untuk mengakui pengeleuaran barang (pengurangan inventory) dan jurnal satunya lagi untuk mengakui penjualannya itu sendiri. Jangan lupa “Penjualaan dalam negeri” adalah terhutang PPn dengan tariff 10%, yang langsung diakui saat pengakuan penjualan. Diakui sebagai utang karena PPn baru disetorkan ke kas negara (melalui bank persepsi) pada tanggal 10 bulan berikutnya.
Pada tanggal 27 February lagi-lagi PT. Royal Bali Cemerlang berhasil menjual barang dagangannya sebanyak 1500 unit dengan unit price yang sama dan masih memakai sistem credit dalam pembayarannya. Sehingga lagi sekali kita jurnal:

Buku Besar dan Inventory Card
Tanggal sudah menunjukkan 29 February 2008, saatnya melakukan “Monthly Closing Book”.
Pertama kita bikin buku besarnya dahulu, dengan jurnal pengakuan import dan penjualan-penjualan diatas dan diasumsikan saldo awal semua rekening adalah 0 (nol), buku besarnya akan menjadi seperti dibawah ini:

Catatan: Perhatikan rekening-rekening pada buku besar di atas dan akan kemana masing-masing rekening tersebut dimasukkan ada yang ke Balance Sheet dan ada yang ke Profit & Lost Statement.
Dan pada “Inventory Card” yang kita di Indonesia biasa menyebutnya “Kartu Stock” (saya sedikit berhati-hati meamaki istilah stock, karena takut bingung dengan saham), dengan asumsi Saldo awal inventory adalah nol, ada pembelian dan penjualan, maka inventory card akan menjadi (tentunya di pastikan terlebih dahulu dengan physical count):

Catatan : Perhatikan rekenening “Inventory” pada buku besar diatas, saldo akhir sama-sama menunjukkan angka Rp 55,777,500,- artinya proses jurnal sudah in synchronized dengan Inventory Card. Great!. Oh ya, diingat-ingat ya angka ini. Lets go to the next step….
Profit & Lost Statement
Ok, so kita sudah punya “Buku Besar” dan “Inventory Card”. Sekarang waktunya kita construct “Profit & Lost Statament”. Session yang paling saya sukai :-)
Profit & Lost Statement pada umumnya terdiri dari :
Revenue, diambil dari rekening Sales pada buku besar, seharunya ada elemen “Other Revenues” i.e.: Bunga Jasa Giro, dan pendapatan lainnya, tetapi pada kasus ini, data-data tersebut tidak tersedia. Maka diambil dari sales saja.
Cost Of Good Sold (Harga Pokok Penjualan), dipecah lagi menjadi : Inventory, Raw Material, Direct Labor Cost, Overhead Cost. Tetapi pada kasus ini, Direct Labor Cost dan Raw Metrial tidak tersedia, sebagai gantinya hanya muncul muncul semua element expenditure sehubungan dengan Import yang sesungguhnya merupakan “Overhead Cost” yang saya munculkan seperti aslinya, agar mudah dipahami.
Gross Profit, didapat dengan formula : Revenue [minus] COGS.
Expenses, adalah biaya-biaya yang muncul sehubungan operasional perusahaan yang tidak dipengaruhi oleh output (produktifitas) perusahaan. Seharusnya ada elemen depreciation/amortization expenses, akan tetapi pada kasus ini saya tidak munculkan agar lebih sederhana.
Earning Before Tax, diperoleh dengan formula: Gross Profit [minus] Expenses
Setelah semua elemen diatas seharusnya ada : Corporate Income Tax (PPh Badan), Earning After Tax (Profit Earning). Tetapi karena kasus ini focus pada penentuan “COGS” saja, maka saya tidak akan bahas di posting ini (kita bahas di postingan yang lain).
Setelah saya construct, semua angka saya masukkan, maka Profit & Lost statement menjadi seperti dibawah ini:
Catatan :

Perhatikan pada element B (COGS/HPP), pada proses import, elemen-elemen apa saja yang dimasukkan. Dan khusus untuk “Inventory” misi kita adalah mencari berapa besarnya “Persediaan Barang Terpakai” dan telah kita peroleh sebesar Rp 162,684,375,- yang didapat dengan formula : Saldo Awal [plus] Pembelian [minus] Persediaan akhir. Persediaan akhir kita peroleh dari buku besar atau inventory Card.
Penerimaan Pelunasan Piutang
Pada tanggal 05 Maret 2008, PT. Royal Bali Cemerlang menerima pelunasan piutang untuk kesemua penjualan yang terjadi pada bulan February, maka dijurnal:

Catatan: Perhatikan catatan dibawah jurnal
Pembayaran PPn
Seperti sudah disampaikan sebelumnya bahwa PPn atas penjualan dalam negeri disetorkan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, maka pada tanggal 09 Maret 2008 dilakukan penyetoran PPn ke kas negara melalaui “Bank Persepsi”, dan atas setoran tersebut dijurnal:

Catatan Penting:
Pada jurnal diatas, pada sisi debit dimasukkan PPn Terhutang, ini akan membuat rekening PPn Terhutang pada Neraca 29 February akan menjadi 0 (nol). Sedangkan pada sisi kredit Cash yang dibayarkan hanya sebesar Rp 3,755,614,- bukan sebesar PPn terhutang, karena PPn Import kita kreditkan saat ini. Ya, kita kreditkan!.
Maka bisa saya katakan disini bahwa: Jika mekanisme proses perhitungan dan pelaporan PPn dilakukan dengan benar, maka prinsip dasar PPn dimana “PPn adalah Pajak Pertambahan Nilai yang artinya, Pajak yang dibayarkan hanyalah sebesar 10% [kali] value added yang berhasil dicreate oleh perusahaan saja”, bukan sebesar 10% [kali] Penjualan Kotor. Pada pembelian bukan import pun ada PPn masukan bukan?. Yang harus diperhatikan disini adalah selalu mintalah Faktur Pajak Masukan anda kepada supplier yang mengenakan PPn atas pembelian raw metrial maupun pembelian lainnya.
PPh Pasal 22 Import
Menjelang pembuatan SPT PPh Badan, dibuatkan jurnal:

Update: 13-Maret-2008
Pada jurnal di atas, seharusnya: [Debit]. PPh Pasal 29 (terhutang), bukan PPh Pasal 22.
Sorry about that.
Catatan: PPh Pasal 22 Import akan menjadi faktor pengurang PPh Pasal 29 nantinya.
Besar harapan saya, artikel ini bisa dipahami sehingga bisa memberikan manfaat bagi pembaca.
Semoga proses penyetoran SPT anda lancar dan sukses.
Senin, 24 Maret 2008
Tarif & cara menghitung PPN & PPn BM
Berapa tarif PPN/PPnBM ?
Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen)
Tarif PPn BM adalah serendah-rendahnya 10% (sepuluh persen) dan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen).
Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah yang atas penyerahan/impor BKP-nya dikenakan PPn BM.
Tarif PPN/ PPn BM atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen).
Apa saja yang termasuk DPP ?
*Harga jual/ penggantian
Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta
oleh penjual/ pembeli jasa karena penyerahan BKP/ Jasa Kena Pajak (JKP), tidak
termasuk PPN/ PPn BM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
*Nilai Impor
Adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah
pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN/ PPn BM.
*Nilai Ekspor
Adalah nilai berupa uang, termasuk semau biaya yang diminta oleh Eksportir.
*Nilai lain
Adalah nilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk
menghitung pajak yang terutang.
Nilai lain tersebut diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 642/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 :
Untuk pemakaian sendiri/ pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian, tidak termasuk laba kotor
Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
Untuk persedian BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;
Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;
Untuk penyerahan jasa biro perjalanan/ parawisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
Untuk PKP Pedagang Eceran (PE) :
PPN yang terutang adalah sebesar 10% (sepuluh persen) x harga jual BKP.
PPN yang harus dibayar adalah sebesar : 10%x20%x jumlah seluruh barang dagangan.
Jasa anjak piutang adalah 5% dari seluruh jumlah imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon.
Bagaimana cara menghitung PPN ?
PPN yang terutang = tarif x DPP
PPN yang terutang merupakan Pajak Keluaran (PK) yang dipungut oleh PKP penjual dan merupakan Pajak Masukan bagi PKP pembeli.
Contoh :
PKP "A" bulan Januari 1996 menjual tunai kepada PKP "B"
100 pasang sepatu @ Rp.100.000,00 = Rp.10.000.000,00
PPN terutang yang dipungut oleh PKP"A"
10% x Rp.10.000.000,00 = Rp. 1.000.000,00
Jumlah yang harus dibayar PKP "B" = Rp.11.000.000,00
PKP "B" dalam bulan Januari 1996 :
Menjual 80 pasang sepatu @ Rp.120.000,00 = Rp. 9.600.000,00
Memakai sendiri 5 pasang sepatu untuk pemakaian sendiri,
DPP adalah harga jual tanpa menghitung laba kotor, yaitu Rp 100.000,- per pasang = Rp 500.000,00
PPN yang terutang :
Atas penjualan 80 pasang sepatu
10% x Rp.9.600.000,00 = Rp 960.000,00
Atas pemakai sendiri
10% x Rp.500.000,00 = Rp 50.000,00
Jumlah PPN terutang = Rp 1.010.000,00
PKP Pedagang Eceran (PE) "C" menjual
BKP seharga = Rp.10.000.000,00
Bukan BKP = Rp. 5.000.000,00
Rp.15.000.000,00
PPN yang terutang
10% x Rp.10.000.000,00 = Rp. 1.000.000,00
PPN yang harus disetor
10% x 20% x Rp.15.000.000,00 = Rp. 300.000,00
PKP "D" pabrikan yang menghasilkan mesin cuci pakaian. Mesin cuci pakaian dikategorikan sebagai BKP yang tergolong mewah dan dikenakan PPn BM dengan tarif sebesar 20%. Dalam bulan Januari 1996 PKP "D" menjual 10 buah mesin cuci kepada PKP "E" seharga Rp.30.000.000,00.
PPN yang terutang
10% x Rp.30.000.000,00 = Rp 3.000.000,00
PPn BM yang terutang
20% x Rp. 30.000.000,000 = Rp 6.000.000,00
PPN dan PPn BM yang terutang PKP "D" = Rp. 9.000.000,00
PKP "E" bulan Januari 1996 menjual 10 buah mesin cuci tersebut diatas seharga Rp.40.000.000,00
PPN yang terutang
10% x Rp.40.000.000,00 = Rp. 4.000.000,00
Catatan :
PKP "E" tidak boleh memungut PPn BM, karena PKP "E" bukan pabrikan dan PPn BM dikenakan hanya sekali.
Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen)
Tarif PPn BM adalah serendah-rendahnya 10% (sepuluh persen) dan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen).
Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah yang atas penyerahan/impor BKP-nya dikenakan PPn BM.
Tarif PPN/ PPn BM atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen).
Apa saja yang termasuk DPP ?
*Harga jual/ penggantian
Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta
oleh penjual/ pembeli jasa karena penyerahan BKP/ Jasa Kena Pajak (JKP), tidak
termasuk PPN/ PPn BM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
*Nilai Impor
Adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah
pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN/ PPn BM.
*Nilai Ekspor
Adalah nilai berupa uang, termasuk semau biaya yang diminta oleh Eksportir.
*Nilai lain
Adalah nilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk
menghitung pajak yang terutang.
Nilai lain tersebut diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 642/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 :
Untuk pemakaian sendiri/ pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian, tidak termasuk laba kotor
Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
Untuk persedian BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;
Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;
Untuk penyerahan jasa biro perjalanan/ parawisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
Untuk PKP Pedagang Eceran (PE) :
PPN yang terutang adalah sebesar 10% (sepuluh persen) x harga jual BKP.
PPN yang harus dibayar adalah sebesar : 10%x20%x jumlah seluruh barang dagangan.
Jasa anjak piutang adalah 5% dari seluruh jumlah imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon.
Bagaimana cara menghitung PPN ?
PPN yang terutang = tarif x DPP
PPN yang terutang merupakan Pajak Keluaran (PK) yang dipungut oleh PKP penjual dan merupakan Pajak Masukan bagi PKP pembeli.
Contoh :
PKP "A" bulan Januari 1996 menjual tunai kepada PKP "B"
100 pasang sepatu @ Rp.100.000,00 = Rp.10.000.000,00
PPN terutang yang dipungut oleh PKP"A"
10% x Rp.10.000.000,00 = Rp. 1.000.000,00
Jumlah yang harus dibayar PKP "B" = Rp.11.000.000,00
PKP "B" dalam bulan Januari 1996 :
Menjual 80 pasang sepatu @ Rp.120.000,00 = Rp. 9.600.000,00
Memakai sendiri 5 pasang sepatu untuk pemakaian sendiri,
DPP adalah harga jual tanpa menghitung laba kotor, yaitu Rp 100.000,- per pasang = Rp 500.000,00
PPN yang terutang :
Atas penjualan 80 pasang sepatu
10% x Rp.9.600.000,00 = Rp 960.000,00
Atas pemakai sendiri
10% x Rp.500.000,00 = Rp 50.000,00
Jumlah PPN terutang = Rp 1.010.000,00
PKP Pedagang Eceran (PE) "C" menjual
BKP seharga = Rp.10.000.000,00
Bukan BKP = Rp. 5.000.000,00
Rp.15.000.000,00
PPN yang terutang
10% x Rp.10.000.000,00 = Rp. 1.000.000,00
PPN yang harus disetor
10% x 20% x Rp.15.000.000,00 = Rp. 300.000,00
PKP "D" pabrikan yang menghasilkan mesin cuci pakaian. Mesin cuci pakaian dikategorikan sebagai BKP yang tergolong mewah dan dikenakan PPn BM dengan tarif sebesar 20%. Dalam bulan Januari 1996 PKP "D" menjual 10 buah mesin cuci kepada PKP "E" seharga Rp.30.000.000,00.
PPN yang terutang
10% x Rp.30.000.000,00 = Rp 3.000.000,00
PPn BM yang terutang
20% x Rp. 30.000.000,000 = Rp 6.000.000,00
PPN dan PPn BM yang terutang PKP "D" = Rp. 9.000.000,00
PKP "E" bulan Januari 1996 menjual 10 buah mesin cuci tersebut diatas seharga Rp.40.000.000,00
PPN yang terutang
10% x Rp.40.000.000,00 = Rp. 4.000.000,00
Catatan :
PKP "E" tidak boleh memungut PPn BM, karena PKP "E" bukan pabrikan dan PPn BM dikenakan hanya sekali.
Tata Cara Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP
Penghapusan NPWP, syarat-syaratnya :
1.WP meninggal dunia dantidak meninggalkan warisan:
a.Fotokopi akta kematian atau;
b.Laporan kematian dari instansi yang berwenang
2.Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, harus ada
surat nikah/akta perkawinan dari Catatan Sipil;
3.Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak, bila telah dibagi
harus ada surat keterangan selesainya pembagian warisan tersebut;
4.WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akta pembubaran;
5.Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang kehilangan statusnya sebgai BUT, harus ada
permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung;
6.WP orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) , syarat-syaratnya :
1.PKP pindah alamat;
2.WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi;
3.PKP lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP
1.WP meninggal dunia dantidak meninggalkan warisan:
a.Fotokopi akta kematian atau;
b.Laporan kematian dari instansi yang berwenang
2.Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, harus ada
surat nikah/akta perkawinan dari Catatan Sipil;
3.Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak, bila telah dibagi
harus ada surat keterangan selesainya pembagian warisan tersebut;
4.WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akta pembubaran;
5.Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang kehilangan statusnya sebgai BUT, harus ada
permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung;
6.WP orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) , syarat-syaratnya :
1.PKP pindah alamat;
2.WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi;
3.PKP lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP
Tata Cara Pendaftaran NPWP
Syarat utama untuk mendaftarkan diri adalah mengisi Formulir Pendaftaran NPWP
Syarat-syarat untuk memperoleh NPWP dan Pengukuhan PKP
1)Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan:
a.Fotokopi KTP atau SIM bagi penduduk Indonesia;
b.Fotokopi Paspor dan surat keteranngan tempat tinggal bagi orang asing
2)Untuk wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan:
a.Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia;
b.Fotokopi? Paspor dan surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing
c.Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang
berwenang
3)Untuk Wajib Pajak Badan
a.Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan
dari kantor pusat bagi BUT
b.Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia salah seorang pengurus;
c.Fotokopi paspor bagi orang asing dan surat keterangan tempat tinggal
d.Surat keterangan tempat kegiatan usaha dri instansi yang berwenang
4)Untuk bendaharawan sebagai pemotong/pemungut :
a.Fotokopi KTP bendaharawan;
b.Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.
5)Untuk Joint operation sebagai wajib pajak pemotong/pemungut:
a.Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation;
b.Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation;
c.Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia dari salah seorang pengurus
d.Fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang
6)Untuk Wajib Pajak berstatus cabang , orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita
kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar
7)Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dengan surat kuasa khusus
Untuk Wajib Pajak Pindah, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :
1)Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan, pindah tempat tinggal/kegiatan usaha:
a.Kartu NPWP
b.surat keterangan tempat tinggal baru dari instansi yang berwenang atau
c.Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
2)Wajib Pajak Orang Pribadi non usaha, pindah tempat tinggal :
a.surat keterangan tempat tinggal baru dari instansi yang berwenang, atau:
b.surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya.
3)Wajib Pajak Badan, pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha :
a.surat keterangan tempat kedudukan atau ;
b.surat keterangan tempat kegiatan baru dari instansi yang berwenang
Syarat-syarat untuk memperoleh NPWP dan Pengukuhan PKP
1)Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan:
a.Fotokopi KTP atau SIM bagi penduduk Indonesia;
b.Fotokopi Paspor dan surat keteranngan tempat tinggal bagi orang asing
2)Untuk wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan:
a.Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia;
b.Fotokopi? Paspor dan surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing
c.Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang
berwenang
3)Untuk Wajib Pajak Badan
a.Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan
dari kantor pusat bagi BUT
b.Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia salah seorang pengurus;
c.Fotokopi paspor bagi orang asing dan surat keterangan tempat tinggal
d.Surat keterangan tempat kegiatan usaha dri instansi yang berwenang
4)Untuk bendaharawan sebagai pemotong/pemungut :
a.Fotokopi KTP bendaharawan;
b.Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.
5)Untuk Joint operation sebagai wajib pajak pemotong/pemungut:
a.Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation;
b.Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation;
c.Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia dari salah seorang pengurus
d.Fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang
6)Untuk Wajib Pajak berstatus cabang , orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita
kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar
7)Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dengan surat kuasa khusus
Untuk Wajib Pajak Pindah, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :
1)Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan, pindah tempat tinggal/kegiatan usaha:
a.Kartu NPWP
b.surat keterangan tempat tinggal baru dari instansi yang berwenang atau
c.Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
2)Wajib Pajak Orang Pribadi non usaha, pindah tempat tinggal :
a.surat keterangan tempat tinggal baru dari instansi yang berwenang, atau:
b.surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya.
3)Wajib Pajak Badan, pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha :
a.surat keterangan tempat kedudukan atau ;
b.surat keterangan tempat kegiatan baru dari instansi yang berwenang
Minggu, 23 Maret 2008
BKP yang dikembalikan
*Dalam hal terjadi pengembalian BKP, tindakan apa yang harus dilakukan oleh pembeli ?
Membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada PKP penjual.
*Sekurang-kurangnya informasi (informasi minimal) apa saja yang harus dicantumkan
dalam nota retur ?
1. Nomor urut;
2. Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan;
3. Nama, alamat, dan NPWP pembeli;
4. Nama, alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan PKP yang
menerbitkan Faktur Pajak;
5. Macam, jenis, kuantum, dan harga jual BKP yang dikembalikan;
6. PPN atas BKP yang dikembalikan;
7. PPn BM atas BKP yang tergolong mewah yang dikembalikan;
8. Tanggal pembuatan Nota Retur;
9. Tanda tangan pembeli.
*Jika nota retur tidak mencantumkan informasi minimal yang disyaratkan, akibat
hukum apa yang akan terjadi ?
Tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur sehingga tidak dapat mengurangi
Pajak Keluaran bagi penjual atau Pajak Masukan, atau harta, atau biaya bagi
pembeli.
*Berapa banyak/rangkap nota retur yang harus dibuat ?
Nota Retur dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) :
* lembar ke-1 : untuk PKP penjual
* lembar ke-2 : untuk arsip pembeli
*Kapan nota retur harus dibuat dan bagaimana bentuk serta ukurannya ?
Nota Retur harus dibuat dalam Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak
terjadinya pengembalian BKP.
Bentuk dan ukuran Nota Retur pada butir 2 dapat disesuaikan dengan kebutuhan
administrasi pembeli.
*Bagaimana pelaporan nota retur dalam SPT Masa PPN ?
* Nota Retur yang dibuat/ diterima harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN, agar
dapat mengurangi PPN/ PPn BM yang telah dilaporkan sebelumnya.
* Pengurangan PPN dan PPN BM oleh PKP penjual dilakukan dalam Masa Pajak
yang sama dengan Masa Pajak dibuatnya Nota Retur.
* Dalam hal Nota Retur belum dapat diperhitungkan dalam Masa Pajak yang sama
dibuatnya Nota Retur, maka Nota Retur dapat diperhitungkan dalam Masa
Pajak diterimanya Nota Retur tersebut.
* Pengurangan PPN dan PPnBM, harta, atau pengurangan biaya oleh pembeli
dilakukan dalam Masa Pajak dibuatnya Nota Retur.
*Bagaimana mekanisme pengembalian BKP yang tidak dibuatkan nota retur ?
* BKP yang dikembalikan diganti dengan BKP yang sama, baik dalam jumlah
fisik, jenis maupun harganya, oleh PKP yang menghasilkan dan menyerahkan
BKP tersebut.
* Atas pengembalian BKP yang terjadi masih dalam Masa Pajak yang sama dengan
terjadinya penyerahan BKP tersebut, tidak harus ditatausahakan sebagai
pengembalian BKP, melainkan dapat ditatausahakan sebagai pembatalan dan/
atau perbaikan atas penyerahan berikut Faktur Pajak yang bersangkutan
untuk memudahkan pengawasan.
*Apa fungsi nota retur bagi pembeli dan penjual yang melakukan penyerahan BKP yang
terutang PPN ?
Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan oleh
pembeli mengurangi :
* Pajak Keluaran bagi Pengusaha Kena Pajak penjual, sepanjang Faktur Pajak (
Faktur Pajak Standar atau Faktur Pajak Sederhana ) atas penyerahan Barang Kena
Pajak tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai.
* Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, sepanjang Pajak
Masukannya dapat dikreditkan dan telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Pertambahan Nilai.
* Harta atau biaya bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak Masukannya
tidak dapat dikreditkan dan telah dikapitalisasi atau telah dibebankan
sebagai biaya.
* Harta atau biaya bagi pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak.
*Apa fungsi nota retur bagi pembeli yang melakukan penyerahan BKP yang terutang PPnBM ?
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak Yang
Tergolong Mewah yang dikembalikan oleh pembeli mengurangi :
* Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak yang
menghasilkan dan menyerahkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, sepanjang
Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut
telah tercantum dalam Faktur Pajak Standar dan telah dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
* Harta atau biaya bagi Pengusaha Kena Pajak yang bertindak sebagai pembeli.
* Harta atau biaya bagi pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak.
Membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada PKP penjual.
*Sekurang-kurangnya informasi (informasi minimal) apa saja yang harus dicantumkan
dalam nota retur ?
1. Nomor urut;
2. Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan;
3. Nama, alamat, dan NPWP pembeli;
4. Nama, alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan PKP yang
menerbitkan Faktur Pajak;
5. Macam, jenis, kuantum, dan harga jual BKP yang dikembalikan;
6. PPN atas BKP yang dikembalikan;
7. PPn BM atas BKP yang tergolong mewah yang dikembalikan;
8. Tanggal pembuatan Nota Retur;
9. Tanda tangan pembeli.
*Jika nota retur tidak mencantumkan informasi minimal yang disyaratkan, akibat
hukum apa yang akan terjadi ?
Tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur sehingga tidak dapat mengurangi
Pajak Keluaran bagi penjual atau Pajak Masukan, atau harta, atau biaya bagi
pembeli.
*Berapa banyak/rangkap nota retur yang harus dibuat ?
Nota Retur dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) :
* lembar ke-1 : untuk PKP penjual
* lembar ke-2 : untuk arsip pembeli
*Kapan nota retur harus dibuat dan bagaimana bentuk serta ukurannya ?
Nota Retur harus dibuat dalam Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak
terjadinya pengembalian BKP.
Bentuk dan ukuran Nota Retur pada butir 2 dapat disesuaikan dengan kebutuhan
administrasi pembeli.
*Bagaimana pelaporan nota retur dalam SPT Masa PPN ?
* Nota Retur yang dibuat/ diterima harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN, agar
dapat mengurangi PPN/ PPn BM yang telah dilaporkan sebelumnya.
* Pengurangan PPN dan PPN BM oleh PKP penjual dilakukan dalam Masa Pajak
yang sama dengan Masa Pajak dibuatnya Nota Retur.
* Dalam hal Nota Retur belum dapat diperhitungkan dalam Masa Pajak yang sama
dibuatnya Nota Retur, maka Nota Retur dapat diperhitungkan dalam Masa
Pajak diterimanya Nota Retur tersebut.
* Pengurangan PPN dan PPnBM, harta, atau pengurangan biaya oleh pembeli
dilakukan dalam Masa Pajak dibuatnya Nota Retur.
*Bagaimana mekanisme pengembalian BKP yang tidak dibuatkan nota retur ?
* BKP yang dikembalikan diganti dengan BKP yang sama, baik dalam jumlah
fisik, jenis maupun harganya, oleh PKP yang menghasilkan dan menyerahkan
BKP tersebut.
* Atas pengembalian BKP yang terjadi masih dalam Masa Pajak yang sama dengan
terjadinya penyerahan BKP tersebut, tidak harus ditatausahakan sebagai
pengembalian BKP, melainkan dapat ditatausahakan sebagai pembatalan dan/
atau perbaikan atas penyerahan berikut Faktur Pajak yang bersangkutan
untuk memudahkan pengawasan.
*Apa fungsi nota retur bagi pembeli dan penjual yang melakukan penyerahan BKP yang
terutang PPN ?
Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan oleh
pembeli mengurangi :
* Pajak Keluaran bagi Pengusaha Kena Pajak penjual, sepanjang Faktur Pajak (
Faktur Pajak Standar atau Faktur Pajak Sederhana ) atas penyerahan Barang Kena
Pajak tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai.
* Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, sepanjang Pajak
Masukannya dapat dikreditkan dan telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Pertambahan Nilai.
* Harta atau biaya bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak Masukannya
tidak dapat dikreditkan dan telah dikapitalisasi atau telah dibebankan
sebagai biaya.
* Harta atau biaya bagi pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak.
*Apa fungsi nota retur bagi pembeli yang melakukan penyerahan BKP yang terutang PPnBM ?
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak Yang
Tergolong Mewah yang dikembalikan oleh pembeli mengurangi :
* Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak yang
menghasilkan dan menyerahkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, sepanjang
Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut
telah tercantum dalam Faktur Pajak Standar dan telah dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
* Harta atau biaya bagi Pengusaha Kena Pajak yang bertindak sebagai pembeli.
* Harta atau biaya bagi pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak.
Saya Adalah Mahasiswa
Saya sadar, memahami, dan akan mengalami bahwa belajar di perguruan tinggi bukan sekadar sarana untuk mendapatkan ijazah melainkan untuk pengembangan diri saya sebagai manusia dengan kepribadian kesarjanaan.
Saya sadar, memahami, dan akan mengalami bahwa nilai ujian saya merupakan konsekuensi logis dari proses belajar yang saya jalankan.
Saya sadar, memahami, dan akan mengalami bahwa pengetahuan dan perilaku saya akan berbeda setelah menempuh suatu mata kuliah dibanding mereka yang tidak sempat belajar di perguruan tinggi.
Saya sadar, memahami, dan akan mengalami bahwa kuliah bukan ajang dehuminasi diri melalui proses dengar kopi melainkan ajang konfirmasi pemahaman terhadap pengetahuan dan penajaman pikiran.
Saya sadar, memahami, dan akan mengalami bahwa tidak ada pelajaran apapun yang sulit dan tidak ada dosen killer karena yang ada dan banyak adalah mahasiswa bunuh diri.
Saya sadar, memahami, dan akan mengalami dan akan menyaksikan bahwa kalau seorang mahasiswa gagal dalam kuliah hal tersebut bukan karena dia bodoh melainkan karena malas atau karena tidak tahu mengapa dia jadi mahasiswa.(Suwardjono:2005)
Saya sadar, memahami, dan akan mengalami bahwa nilai ujian saya merupakan konsekuensi logis dari proses belajar yang saya jalankan.
Saya sadar, memahami, dan akan mengalami bahwa pengetahuan dan perilaku saya akan berbeda setelah menempuh suatu mata kuliah dibanding mereka yang tidak sempat belajar di perguruan tinggi.
Saya sadar, memahami, dan akan mengalami bahwa kuliah bukan ajang dehuminasi diri melalui proses dengar kopi melainkan ajang konfirmasi pemahaman terhadap pengetahuan dan penajaman pikiran.
Saya sadar, memahami, dan akan mengalami bahwa tidak ada pelajaran apapun yang sulit dan tidak ada dosen killer karena yang ada dan banyak adalah mahasiswa bunuh diri.
Saya sadar, memahami, dan akan mengalami dan akan menyaksikan bahwa kalau seorang mahasiswa gagal dalam kuliah hal tersebut bukan karena dia bodoh melainkan karena malas atau karena tidak tahu mengapa dia jadi mahasiswa.(Suwardjono:2005)
Sabtu, 22 Maret 2008
PTKP
PTKP adalah singkatan dari penghasilan tidak kena pajak. Sebelum kenakan tarif progresif, penghasilan neto dikurangi dulu dengan PTKP. PTKP berlaku hanya untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP). Untuk wajib pajak badan seperti : perseroan terbatas, CV, yayasan, lembaga, dan badan lain, tidak dapat menggunakan PTKP.
PTKP sebenarnya ditujukan untuk penghasilan minimum yang dapat dinikmati oleh wajib pajak untuk tetap hidup walaupun sederhana. Istilah yang berkembang di perburuhan adalah UMK atau upah minimum kabupaten. Karena itu, per teori, PTKP tidak boleh lebih kecil daripada UMK.
Beberapa tahun yang lalu, PTKP sempat berada dibawah UMK. Kemudian, DJP memberikan keringanan dengan “PPh ditanggung pemerintah”. Maksudnya, pajak penghasilan atas selisih antara PTKP dan UMK dibebaskan. Pajak yang benar-benar terutang hanya untuk yang diatas UMK.
Tetapi sejak tahun 2005, PTKP dinaikan menjadi Rp. 12.000.000 per WP OP. Dan tahun 2006, PTKP dinaikan lagi menjadi Rp. 13.200.000! Dengan demikian, sekarang PTKP jauh diatas UMK. Jadi, jangan khawatir, para buruh yang digaji dengan UMK pasti bebas pajak penghasilan!!!
Karena maksud dari PTKP untuk kebutuhan minimum, penghasilan untuk kebutuhan minimum, maka jika WP OP memiliki istri dan tanggungan maka PTKP juga bertambah. Maaf, UU PPh 1984 memandang bahwa pencari rejeki (penghasilan) adalah suami. Sehingga jika seorang istri bekerja dan suaminya pengangguran maka untuk mendapatkan PTKP tanggungan suami, si istri tersebut harus mendapatkan keterangan dari kantor kecamatan!
Berikut adalah jumlah PTKP yang dapat dikurangkan dari penghasilan neto WP OP yang berstatus bujangan:
1. WP tidak Kawin dan tidak memiliki Tanggungan, Rp 13,200,000
2. WP tidak Kawin dan memiliki Tanggungan 1 Orang, Rp 14,400,000
3. WP tidak Kawin dan memiliki Tanggungan 2 Orang, Rp 15,600,000
4. WP tidak Kawin dan memiliki Tanggungan 3 Orang, Rp 16,800,000
Berikut adalah jumlah PTKP yang dapat dikurangkan dari penghasilan neto WP OP yang berstatus kawin, istri tidak punya penghasilan, atau punya penghasilan tapi ada perjanjian pisah harta:
1. WP Kawin, dan tidak memiliki Tanggungan, Rp 14,400,000
2. WP Kawin, dan memiliki Tanggungan 1 Orang, Rp 15,600,000
3. WP Kawin, dan memiliki Tanggungan 2 Orang, Rp 16,800,000
4. WP Kawin, dan memiliki Tanggungan 3 Orang, Rp 18,000,000
Berikut adalah jumlah PTKP yang dapat dikurangkan dari penghasilan neto WP OP yang berstatus kawin, istri punya penghasilan dan penghasilan tersebut digabung dengan penghasilan suami di SPT PPh :
1. WP Kawin, dan tidak memiliki Tanggungan, Rp 27,600,000
2. WP Kawin, dan memiliki Tanggungan 1 Orang, Rp 28,800,000
3. WP Kawin, dan memiliki Tanggungan 2 Orang, Rp 30,000,000
4. WP Kawin, dan memiliki Tanggungan 3 Orang, Rp 31,200,000
Dari perincian diatas jelaslah jika istri punya penghasilan lain, maka PTKP lebih besar daripada istri tidak punya penghasilan lain. Karena itu, salah satu trik mengisi SPT Tahunan PPh adalah dengan menyuruh istri dagang, dan hasil dagangannya digabung. Namanya jualan, bisa rugi, bisa untung 100 ribu rupiah, atau untung 100 milyar rupiah. He .. he .. he …
PTKP sebenarnya ditujukan untuk penghasilan minimum yang dapat dinikmati oleh wajib pajak untuk tetap hidup walaupun sederhana. Istilah yang berkembang di perburuhan adalah UMK atau upah minimum kabupaten. Karena itu, per teori, PTKP tidak boleh lebih kecil daripada UMK.
Beberapa tahun yang lalu, PTKP sempat berada dibawah UMK. Kemudian, DJP memberikan keringanan dengan “PPh ditanggung pemerintah”. Maksudnya, pajak penghasilan atas selisih antara PTKP dan UMK dibebaskan. Pajak yang benar-benar terutang hanya untuk yang diatas UMK.
Tetapi sejak tahun 2005, PTKP dinaikan menjadi Rp. 12.000.000 per WP OP. Dan tahun 2006, PTKP dinaikan lagi menjadi Rp. 13.200.000! Dengan demikian, sekarang PTKP jauh diatas UMK. Jadi, jangan khawatir, para buruh yang digaji dengan UMK pasti bebas pajak penghasilan!!!
Karena maksud dari PTKP untuk kebutuhan minimum, penghasilan untuk kebutuhan minimum, maka jika WP OP memiliki istri dan tanggungan maka PTKP juga bertambah. Maaf, UU PPh 1984 memandang bahwa pencari rejeki (penghasilan) adalah suami. Sehingga jika seorang istri bekerja dan suaminya pengangguran maka untuk mendapatkan PTKP tanggungan suami, si istri tersebut harus mendapatkan keterangan dari kantor kecamatan!
Berikut adalah jumlah PTKP yang dapat dikurangkan dari penghasilan neto WP OP yang berstatus bujangan:
1. WP tidak Kawin dan tidak memiliki Tanggungan, Rp 13,200,000
2. WP tidak Kawin dan memiliki Tanggungan 1 Orang, Rp 14,400,000
3. WP tidak Kawin dan memiliki Tanggungan 2 Orang, Rp 15,600,000
4. WP tidak Kawin dan memiliki Tanggungan 3 Orang, Rp 16,800,000
Berikut adalah jumlah PTKP yang dapat dikurangkan dari penghasilan neto WP OP yang berstatus kawin, istri tidak punya penghasilan, atau punya penghasilan tapi ada perjanjian pisah harta:
1. WP Kawin, dan tidak memiliki Tanggungan, Rp 14,400,000
2. WP Kawin, dan memiliki Tanggungan 1 Orang, Rp 15,600,000
3. WP Kawin, dan memiliki Tanggungan 2 Orang, Rp 16,800,000
4. WP Kawin, dan memiliki Tanggungan 3 Orang, Rp 18,000,000
Berikut adalah jumlah PTKP yang dapat dikurangkan dari penghasilan neto WP OP yang berstatus kawin, istri punya penghasilan dan penghasilan tersebut digabung dengan penghasilan suami di SPT PPh :
1. WP Kawin, dan tidak memiliki Tanggungan, Rp 27,600,000
2. WP Kawin, dan memiliki Tanggungan 1 Orang, Rp 28,800,000
3. WP Kawin, dan memiliki Tanggungan 2 Orang, Rp 30,000,000
4. WP Kawin, dan memiliki Tanggungan 3 Orang, Rp 31,200,000
Dari perincian diatas jelaslah jika istri punya penghasilan lain, maka PTKP lebih besar daripada istri tidak punya penghasilan lain. Karena itu, salah satu trik mengisi SPT Tahunan PPh adalah dengan menyuruh istri dagang, dan hasil dagangannya digabung. Namanya jualan, bisa rugi, bisa untung 100 ribu rupiah, atau untung 100 milyar rupiah. He .. he .. he …
PPh Terutang
Penghasilan Kena Pajak adalah dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh 1984 dengan semua biaya, kecuali biaya yang dikecualikan, dan PTKP bagi WP OP.
Penghasilan disini tentu saja bukan penghasilan final, dan bukan penghasilan bukan objek. Pemisahan ini sengaja saya ulang-ulang karena jika digabung akan merugikan wajib pajak itu sendiri. Penggabungan penghasilan final dan bukan objek dengan penghasilan kena pajak akan membuat PPh terutang lebih tinggi daripada seharusnya. Dan, beberapa wajib pajak masih saja melakukan kesalahan ini.
Jadi formulanya sebagai berikut:
Penghasilan – Biaya – PTKP = Penghasilan Kena Pajak
PPh Terutang = Penghasilan Kena Pajak x Tarif
Sedangkan tarif yang berlaku, saat ini, terbagi dua macam, yaitu untuk WP OP dan untuk WP badan. Berikut perbedaannya :
Tarif PPh terutang utang WP OP :
sampai dengan Rp 25.000.000,00, sebesar 5%
di atas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00, sebesar 10%
di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp.100.000.000,00, sebesar 15%
di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp.200.000.000,00, sebesar 25%
di atas Rp 200.000.000,00, sebesar 35%
Tarif PPh terutang utang WP badan :
Sampai dengan Rp 50.000.000,00, sebesar 10%
di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp.100.000.000,00, sebesar 15%
di atas Rp 100.000.000,00, sebesar 30%
Contoh penghitungan pajak terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi
Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 250.000.000,00
Pajak Penghasilan terutang :
5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00
25% x Rp 100.000.000,00 =Rp 25.000.000,00
35% x Rp 50.000.000,00 = Rp 17.500.000,00
Total PPh terutang Rp 53.750.000, 00
Penghasilan disini tentu saja bukan penghasilan final, dan bukan penghasilan bukan objek. Pemisahan ini sengaja saya ulang-ulang karena jika digabung akan merugikan wajib pajak itu sendiri. Penggabungan penghasilan final dan bukan objek dengan penghasilan kena pajak akan membuat PPh terutang lebih tinggi daripada seharusnya. Dan, beberapa wajib pajak masih saja melakukan kesalahan ini.
Jadi formulanya sebagai berikut:
Penghasilan – Biaya – PTKP = Penghasilan Kena Pajak
PPh Terutang = Penghasilan Kena Pajak x Tarif
Sedangkan tarif yang berlaku, saat ini, terbagi dua macam, yaitu untuk WP OP dan untuk WP badan. Berikut perbedaannya :
Tarif PPh terutang utang WP OP :
sampai dengan Rp 25.000.000,00, sebesar 5%
di atas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00, sebesar 10%
di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp.100.000.000,00, sebesar 15%
di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp.200.000.000,00, sebesar 25%
di atas Rp 200.000.000,00, sebesar 35%
Tarif PPh terutang utang WP badan :
Sampai dengan Rp 50.000.000,00, sebesar 10%
di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp.100.000.000,00, sebesar 15%
di atas Rp 100.000.000,00, sebesar 30%
Contoh penghitungan pajak terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi
Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 250.000.000,00
Pajak Penghasilan terutang :
5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00
25% x Rp 100.000.000,00 =Rp 25.000.000,00
35% x Rp 50.000.000,00 = Rp 17.500.000,00
Total PPh terutang Rp 53.750.000, 00
Norma Perhitungan
Tidak semua Wajib Pajak tentu memiliki kemampuan untuk membuat pembukuan. Justru pada umumnya, pengusahan kita mayoritas masih pada taraf usaha kecil. Mereka sangat mungkin tidak memiliki kemampuan membuat pembukuan. Selain itu, para profesional yang memiliki praktek profesi sendiri mungkin saja tidak memiliki pembukuan. Nah, bagi mereka yang tidak mau membuat pembukuan, Direktorat Jenderal Pajak telah membuat Norma Penghitungan.
Norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Norma penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto. Penggunaan Norma Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal :
a. tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau
b. pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.
Norma penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajaran. Aplikasinya, Norma Penghitungan itu merupakan persentase tertentu untuk mencari penghasilan neto. Wajib Pajak tidak perlu merinci berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk mencari penghasilan neto.
Formula umum untuk mencari penghasilan neto itu : penghasilan kotor – biaya = penghasilan neto.
Tetapi formula Norma Penghitungan untuk mencari penghasilan neto adalah :
penghasilan kotor x Norma = penghasilan neto.
Saya ingatkan kembali, untuk mencari PPh terutang untuk WP OP, penghasilan neto masih dikurangi lagi dengan PTKP. Sehingga formula lengkap untuk mencari PPh terutang adalah :
((Penghasilan kotor x Norma) – PTKP) x Tarif = PPh Terutang
Pemilihan Norma Penghasilan bagi Wajib Pajak memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah sederhana. Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan yang lengkap. Wajib Pajak tidak perlu membuat laporan keuangan seperti Neraca (balance sheet), dan Laporan Laba Rugi (income statement). Wajib Pajak cukup membuat catatan penghasilan kotor!!!
Kerugiannya adalah tidak pernah rugi. Yah, bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan Norma Penghitungan maka usahanya tidak akan pernah rugi. Selalu untung! Pada kenyataannya, namanya usaha ada untung, ada rugi bukan?
Seperti dijelaskan diatas, Norma Penghitungan dibuat berdasarkan penelitian. Artinya, Norma Penghitungan dibuat dengan moderat atau pertengahan. Karena itu, pada prakteknya mungkin laba usaha kita bisa diatas atau dibawah Norma Penghitungan. Karena itu, jika laba usaha (persentase keuntungan) kita tinggi maka akan menguntungkan jika penghasilan neto menggunakan Norma Penghitungan. Jika sebaliknya, persentase keuntungan kita kecil, Wajib Pajak sebenarnya rugi menggunakan Norma Penghitungan.
Jadi, jelaslah jika Norma Penghitungan mengabaikan unsur keadilan. Memang tujuan Norma Penghitungan sekedar penyederhanaan penghitungan penghasilan bersih. Jika menginginkan keadilan, maka kita mesti repot-repot membuat pembukuan dan laporan keuangan.
Tidak semua Wajib Pajak dapat menggunakan Norma Penghitungan. Hanya Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang memiliki total penjualan (omset) setahun sampai dengan Rp.600 juta sajalah. Tetapi sejak Januari 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.03/2007 batas penghasilan menjadi Rp1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah). Jika total penjualan melebihi angka tersebut, atau WP badan, maka WAJIB menggunakan pembukuan dan menyusun laporan keuangan.
Selain itu, untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut Wajib Pajak orang pribadi harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
Norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Norma penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto. Penggunaan Norma Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal :
a. tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau
b. pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.
Norma penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajaran. Aplikasinya, Norma Penghitungan itu merupakan persentase tertentu untuk mencari penghasilan neto. Wajib Pajak tidak perlu merinci berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk mencari penghasilan neto.
Formula umum untuk mencari penghasilan neto itu : penghasilan kotor – biaya = penghasilan neto.
Tetapi formula Norma Penghitungan untuk mencari penghasilan neto adalah :
penghasilan kotor x Norma = penghasilan neto.
Saya ingatkan kembali, untuk mencari PPh terutang untuk WP OP, penghasilan neto masih dikurangi lagi dengan PTKP. Sehingga formula lengkap untuk mencari PPh terutang adalah :
((Penghasilan kotor x Norma) – PTKP) x Tarif = PPh Terutang
Pemilihan Norma Penghasilan bagi Wajib Pajak memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah sederhana. Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan yang lengkap. Wajib Pajak tidak perlu membuat laporan keuangan seperti Neraca (balance sheet), dan Laporan Laba Rugi (income statement). Wajib Pajak cukup membuat catatan penghasilan kotor!!!
Kerugiannya adalah tidak pernah rugi. Yah, bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan Norma Penghitungan maka usahanya tidak akan pernah rugi. Selalu untung! Pada kenyataannya, namanya usaha ada untung, ada rugi bukan?
Seperti dijelaskan diatas, Norma Penghitungan dibuat berdasarkan penelitian. Artinya, Norma Penghitungan dibuat dengan moderat atau pertengahan. Karena itu, pada prakteknya mungkin laba usaha kita bisa diatas atau dibawah Norma Penghitungan. Karena itu, jika laba usaha (persentase keuntungan) kita tinggi maka akan menguntungkan jika penghasilan neto menggunakan Norma Penghitungan. Jika sebaliknya, persentase keuntungan kita kecil, Wajib Pajak sebenarnya rugi menggunakan Norma Penghitungan.
Jadi, jelaslah jika Norma Penghitungan mengabaikan unsur keadilan. Memang tujuan Norma Penghitungan sekedar penyederhanaan penghitungan penghasilan bersih. Jika menginginkan keadilan, maka kita mesti repot-repot membuat pembukuan dan laporan keuangan.
Tidak semua Wajib Pajak dapat menggunakan Norma Penghitungan. Hanya Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang memiliki total penjualan (omset) setahun sampai dengan Rp.600 juta sajalah. Tetapi sejak Januari 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.03/2007 batas penghasilan menjadi Rp1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah). Jika total penjualan melebihi angka tersebut, atau WP badan, maka WAJIB menggunakan pembukuan dan menyusun laporan keuangan.
Selain itu, untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut Wajib Pajak orang pribadi harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
Sekilas ttg PPh 21 (Part 2)
Ini adalah bagian pertama dari kredit pajak. Kredit pajak adalah pajak yang telah kita bayar kepada negara. Kredit pajak seharusnya merupakan kebanggaan sebagai warga negara terhadap negaranya.
PPh Pasal 21 merupakan PPh yang dipotong oleh majikan. Pada awalnya, pasal ini diperuntukkan hanya untuk pegawai, karyawan, atau Wajib Pajak yang berstatus bukan bos atau majikan. Tetapi pada perkembangannya, kalangan profesi juga sering menggunakan pasal ini. Misalnya, seorang konsultan memberikan konsultasi kepada kliennya. Pembayaran yang diterima oleh konsultan tersebut dipotong PPh Pasal 21 terlebih dahulu sebelum diterima konsultan.
Jadi, siapa yang dianggap “majikan”? UU PPh 1984 memberikan tugas kepada pemberi penghasilan berikut untuk memotong PPh Pasal 21:
a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
Pada huruf “d” diatas jelaslah bahwa penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas wajib dipotong PPh Pasal 21. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang berstatus bebas, independen, dan tidak terikat. Posisi antara pemberi kerja dengan pelaksana kerja setara. Begitu juga yang dimaksudkan pada huruf “e” diatas.
Bagaimana memotong PPh Pasal 21? Pada umumnya PPh Pasal 21 dihitung dari PPh terutang dibagi 12. Sehingga setiap bulan karyawan tersebut dipotong PPh Pasal 21 sekian rupiah. Idealnya, dan ini yang dikehendaki DJP dengan buku petunjuk pemotongan, PPh karyawan itu habis dibagi per bulan. Artinya, saat membuat SPT PPh Pasal 21 Tahunan, tidak ada lagi PPh yang kurang bayar.
Tetapi pada prakteknya, kebanyakan SPT PPh Pasal 21 Tahunan masih kurang bayar. Mungkin ini disengaja untuk keperluan tertentu. Bisa juga karena ketidaktahuan. Atau mungkin berprinsip : sekedar nyicil, yang penting PPh karyawan dibayar lunas. Apapun pilihannya, catatan yang paling penting adalah : bayarlah PPh Pasal 21!
Ada penghasilan ada biaya. Jarang sekali kita mendapatkan penghasilan tanpa mengeluarkan biaya. Nah, di PPh Pasal 21 ada istilah biaya jabatan, dan biaya pensiun. Walaupun angka biaya tersebut kecil, tetapi angka tersebut dimaksudkan sebagai biaya (pengurang) untuk mendapatkan penghasilan pegawai. Bukankah hampir setiap pegawai mengeluarkan biaya transportasi untuk mencapai tempat kerja?
Selain biaya jabatan, faktor pengurang penghasilan di PPh Pasal 21 adalah iuran pensiun. Iuran pensiun adalah penghasilan yang kita sisihkan untuk disimpan di Dana Pensiun. Penghasilan yang kita sisihkan tersebut tidak dikenakan pajak karena akan dikenakan PPh Pasal 21 saat kita terima pensiunan dari Dana Pensiun.
Berbeda dengan iuran dana pensiun, premi asuransi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan pegawai. Perlakuan perpajakan asuransi jiwa dibedakan dengan dengan Dana Pensiun. Jika pensiunan yang kita terima dari Dana Pensiun akan dipotong PPh Pasal 21 maka klaim dari asuransi jiwa sudah bebas pajak. Penghasilan yang kita sisihkan untuk membayar premi asuransi jiwa pajaknya sudah lunas.
PPh Pasal 21 merupakan PPh yang dipotong oleh majikan. Pada awalnya, pasal ini diperuntukkan hanya untuk pegawai, karyawan, atau Wajib Pajak yang berstatus bukan bos atau majikan. Tetapi pada perkembangannya, kalangan profesi juga sering menggunakan pasal ini. Misalnya, seorang konsultan memberikan konsultasi kepada kliennya. Pembayaran yang diterima oleh konsultan tersebut dipotong PPh Pasal 21 terlebih dahulu sebelum diterima konsultan.
Jadi, siapa yang dianggap “majikan”? UU PPh 1984 memberikan tugas kepada pemberi penghasilan berikut untuk memotong PPh Pasal 21:
a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
Pada huruf “d” diatas jelaslah bahwa penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas wajib dipotong PPh Pasal 21. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang berstatus bebas, independen, dan tidak terikat. Posisi antara pemberi kerja dengan pelaksana kerja setara. Begitu juga yang dimaksudkan pada huruf “e” diatas.
Bagaimana memotong PPh Pasal 21? Pada umumnya PPh Pasal 21 dihitung dari PPh terutang dibagi 12. Sehingga setiap bulan karyawan tersebut dipotong PPh Pasal 21 sekian rupiah. Idealnya, dan ini yang dikehendaki DJP dengan buku petunjuk pemotongan, PPh karyawan itu habis dibagi per bulan. Artinya, saat membuat SPT PPh Pasal 21 Tahunan, tidak ada lagi PPh yang kurang bayar.
Tetapi pada prakteknya, kebanyakan SPT PPh Pasal 21 Tahunan masih kurang bayar. Mungkin ini disengaja untuk keperluan tertentu. Bisa juga karena ketidaktahuan. Atau mungkin berprinsip : sekedar nyicil, yang penting PPh karyawan dibayar lunas. Apapun pilihannya, catatan yang paling penting adalah : bayarlah PPh Pasal 21!
Ada penghasilan ada biaya. Jarang sekali kita mendapatkan penghasilan tanpa mengeluarkan biaya. Nah, di PPh Pasal 21 ada istilah biaya jabatan, dan biaya pensiun. Walaupun angka biaya tersebut kecil, tetapi angka tersebut dimaksudkan sebagai biaya (pengurang) untuk mendapatkan penghasilan pegawai. Bukankah hampir setiap pegawai mengeluarkan biaya transportasi untuk mencapai tempat kerja?
Selain biaya jabatan, faktor pengurang penghasilan di PPh Pasal 21 adalah iuran pensiun. Iuran pensiun adalah penghasilan yang kita sisihkan untuk disimpan di Dana Pensiun. Penghasilan yang kita sisihkan tersebut tidak dikenakan pajak karena akan dikenakan PPh Pasal 21 saat kita terima pensiunan dari Dana Pensiun.
Berbeda dengan iuran dana pensiun, premi asuransi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan pegawai. Perlakuan perpajakan asuransi jiwa dibedakan dengan dengan Dana Pensiun. Jika pensiunan yang kita terima dari Dana Pensiun akan dipotong PPh Pasal 21 maka klaim dari asuransi jiwa sudah bebas pajak. Penghasilan yang kita sisihkan untuk membayar premi asuransi jiwa pajaknya sudah lunas.
Sekilas ttg PPh 21
PPh Pasal 21 adalah salah satu pajak penghasilan yang memiliki banyak rumus berdasarkan profesi, keadaan, dan jenis penghasilan. Formula-formula dibawah ini, mudah-mudahan, dapat membantu cara menghitung PPh Pasal 21 terutang.
Tetapi sebelum ke formula, saya jelaskan dulu singkatan yang digunakan :
PB = penghasilan bruto, total semua penghasilan yang diterima.
BJ = biaya jabatan, 5% dari penghasilan tetapi maksimal Rp. 108 ribu per bulan.
BP = biaya pensiun, 5% dari pensiunan tetapi maksimal Rp. 36 ribu per bulan.
IP = iuran pensiun, sesuai yang dibayarkan ke Dana Pensiun.
Tarif Pasal 17 = tarif progresif berdasarkan Pasal 17 UU PPh 1984
Penghasilan Teratur yang diterima oleh Pegawai Tetap
(PB – (BJ + IP) – PTKP) x Tarif Pasal 17
Upah yang Diterima oleh Tenaga Harian Lepas di atas Rp. 110.000/hari tetapi tidak lebih dari Rp. 1.100.000/bulan
(PB – Rp. 110.000) x 5%
Upah yang Diterima oleh Tenaga Harian Lepas tidak lebih dari Rp. 110.000/hari namun lebih dari Rp. 1.100.000/bulan
(PB – PTKP sebenarnya) x 5%
Rabat/Komisi Penjualan yang diterima oleh Distributor MLM/Direct Selling dan kegiatan sejenis [dihitung per bulan]
(PB – PTKP) x Tarif Pasal 17
Uang Tebusan Pensiun, Uang THT atau JHT, Uang Pesangon [ FINAL ]
Rp. 25 juta s.d Rp. 50 juta = PB x 5%
Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta = PB x 10%
Rp. 100 juta s.d Rp. 200 juta = PB x 15%
Diatas Rp. 200 juta = PB x 25%
Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus yang diterima Mantan Pegawai
PB x Tarif Pasal 17
Honorarium yang diterima Dewan Komisaris/Pengawas yang bukan pegawai tetap pada perusahaan yang sama
PB x Tarif Pasal 17
Uang Pensiun Bulanan yang diterima pensiunan
((PB – BP) – PTKP) x Tarif Pasal 17
Penarikan dana pada Dana Pensiun oleh Pensiunan
PB x Tarif Pasal 17
Honorarium dan Pembayaran Lain yang diterima oleh Tenaga Ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris) sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan
PB x 7,5%
Honorarium yang diterima oleh Pegawai Tidak Tetap, Pemagang, Calon Pegawai
(PB – PTKP) x Tarif Pasal 17
Honorarium dan pembayaran lain yang diterima oleh Tenaga Lepas (Seniman, Olahragawan, Penceramah, Pemberi Jasa, Pengelola Proyek, Peserta Perlombaan, PDL Asuransi, dll)
PB x Tarif Pasal 17
Penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang telah berstatus sebagai WPDN
((PB – (BJ + IP) – PTKP) x Tarif Pasal 17
Penghasilan dari pekerjaan yang diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang bekerja pada Perusahaan Pengeboran Migas [penghasilan per bulan]:
a. General Manager = US$ 11.275 x Tarif Pasal 17
b. Manager = US$ 9.350 x Tarif Pasal 17
c. Supervisor/Tool Pusher = US$ 5.830 x Tarif Pasal 17
d. Assisten Supervisor/Tool Pusher = US$ 4.510 x Tarif Pasal 17
e. Crew Lainnya = US$ 3.245 x Tarif Pasal 17
Tetapi sebelum ke formula, saya jelaskan dulu singkatan yang digunakan :
PB = penghasilan bruto, total semua penghasilan yang diterima.
BJ = biaya jabatan, 5% dari penghasilan tetapi maksimal Rp. 108 ribu per bulan.
BP = biaya pensiun, 5% dari pensiunan tetapi maksimal Rp. 36 ribu per bulan.
IP = iuran pensiun, sesuai yang dibayarkan ke Dana Pensiun.
Tarif Pasal 17 = tarif progresif berdasarkan Pasal 17 UU PPh 1984
Penghasilan Teratur yang diterima oleh Pegawai Tetap
(PB – (BJ + IP) – PTKP) x Tarif Pasal 17
Upah yang Diterima oleh Tenaga Harian Lepas di atas Rp. 110.000/hari tetapi tidak lebih dari Rp. 1.100.000/bulan
(PB – Rp. 110.000) x 5%
Upah yang Diterima oleh Tenaga Harian Lepas tidak lebih dari Rp. 110.000/hari namun lebih dari Rp. 1.100.000/bulan
(PB – PTKP sebenarnya) x 5%
Rabat/Komisi Penjualan yang diterima oleh Distributor MLM/Direct Selling dan kegiatan sejenis [dihitung per bulan]
(PB – PTKP) x Tarif Pasal 17
Uang Tebusan Pensiun, Uang THT atau JHT, Uang Pesangon [ FINAL ]
Rp. 25 juta s.d Rp. 50 juta = PB x 5%
Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta = PB x 10%
Rp. 100 juta s.d Rp. 200 juta = PB x 15%
Diatas Rp. 200 juta = PB x 25%
Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus yang diterima Mantan Pegawai
PB x Tarif Pasal 17
Honorarium yang diterima Dewan Komisaris/Pengawas yang bukan pegawai tetap pada perusahaan yang sama
PB x Tarif Pasal 17
Uang Pensiun Bulanan yang diterima pensiunan
((PB – BP) – PTKP) x Tarif Pasal 17
Penarikan dana pada Dana Pensiun oleh Pensiunan
PB x Tarif Pasal 17
Honorarium dan Pembayaran Lain yang diterima oleh Tenaga Ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris) sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan
PB x 7,5%
Honorarium yang diterima oleh Pegawai Tidak Tetap, Pemagang, Calon Pegawai
(PB – PTKP) x Tarif Pasal 17
Honorarium dan pembayaran lain yang diterima oleh Tenaga Lepas (Seniman, Olahragawan, Penceramah, Pemberi Jasa, Pengelola Proyek, Peserta Perlombaan, PDL Asuransi, dll)
PB x Tarif Pasal 17
Penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang telah berstatus sebagai WPDN
((PB – (BJ + IP) – PTKP) x Tarif Pasal 17
Penghasilan dari pekerjaan yang diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang bekerja pada Perusahaan Pengeboran Migas [penghasilan per bulan]:
a. General Manager = US$ 11.275 x Tarif Pasal 17
b. Manager = US$ 9.350 x Tarif Pasal 17
c. Supervisor/Tool Pusher = US$ 5.830 x Tarif Pasal 17
d. Assisten Supervisor/Tool Pusher = US$ 4.510 x Tarif Pasal 17
e. Crew Lainnya = US$ 3.245 x Tarif Pasal 17
Selasa, 18 Maret 2008
Sekilas ttg PPh 22
Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain [ Pasal 22 ayat (1) UU PPh 1984 ]
Berdasarkan ketentuan ini yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah bendaharawan pemerintah dan badan – badan tertentu :
a. bendaharawan pemerintah, termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Tarif pemungutan PPh Pasal 22 oleh bendaharawan pemerintah adalah 1,5% dari pembelian.
b. badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor, atau kegiatan usaha di bidang lain.
Tarif pemungutan PPh Pasal 22 yang berkenaan dengan kegiatan impor ada dua, yaitu : 2,5% dari harga impor untuk impor yang dilakukan importer yang memiliki Angka Pengenal Impor (API). Dan, 7,5% dari harga impor untuk impor yang dilakukan importer yang tidak memiliki Angka Pengenal Impor (Non API). Selain itu,tariff 7,5% dari harga lelang juga dipungut PPh Pasal 22 untuk impor yang telantar atau tidak dikuasai.
Sedangkan badan-badan yang memiliki kegiatan usaha tertentu yang diwajibkan memungut PPh Pasal 22 adalah:
a. Industri Semen, tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari penjualan
b. Industri Rokok, tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,15% dari harga banderol [FINAL]
c. Industri Kertas, tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,1% dari penjualan
d. Industri Baja, tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,3% dari penjualan
e. Industri Otomotif, tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,45% dari penjualan
f. Industri Migas, terdiri dari [FINAL] :
[1] BBM jenis Premium, untuk SPBU swasta tarifnya 0,3% dan untuk SPBU Pertamina tarifnya 0,25%;
[2] BBM jenis Solar, untuk SPBU swasta tarifnya 0,3% dan untuk SPBU Pertamina tarifnya 0,25%;
[3] BBM jenis Pertamax / Pertamax plus, untuk SPBU swasta tarifnya 0,3% dan untuk SPBU Pertamina tarifnya 0,25%;
[4] BBM jenis Minyak Tanah, untuk SPBU Pertamina tarifnya 0,3%;
[5] BBM jenis gas / LPG, untuk SPBU Pertamina tarifnya 0,3%;
[6] Pelumas Pertamina di SPBU Pertamina, tarifnya 0,3%
Maksud pemungutan ini untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Tetapi harus diingat bahwa kesederhanaan pemungutan pajak selalu berlawanan dengan keadilan. Sebagai contoh pengenaan PPh Final untuk industri migas. Kenapa perusahaan migas hanya membayar 0,25% dari penjualan? Bandingkan dengan industri dagang lain!
Berdasarkan ketentuan ini yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah bendaharawan pemerintah dan badan – badan tertentu :
a. bendaharawan pemerintah, termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Tarif pemungutan PPh Pasal 22 oleh bendaharawan pemerintah adalah 1,5% dari pembelian.
b. badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor, atau kegiatan usaha di bidang lain.
Tarif pemungutan PPh Pasal 22 yang berkenaan dengan kegiatan impor ada dua, yaitu : 2,5% dari harga impor untuk impor yang dilakukan importer yang memiliki Angka Pengenal Impor (API). Dan, 7,5% dari harga impor untuk impor yang dilakukan importer yang tidak memiliki Angka Pengenal Impor (Non API). Selain itu,tariff 7,5% dari harga lelang juga dipungut PPh Pasal 22 untuk impor yang telantar atau tidak dikuasai.
Sedangkan badan-badan yang memiliki kegiatan usaha tertentu yang diwajibkan memungut PPh Pasal 22 adalah:
a. Industri Semen, tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari penjualan
b. Industri Rokok, tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,15% dari harga banderol [FINAL]
c. Industri Kertas, tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,1% dari penjualan
d. Industri Baja, tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,3% dari penjualan
e. Industri Otomotif, tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,45% dari penjualan
f. Industri Migas, terdiri dari [FINAL] :
[1] BBM jenis Premium, untuk SPBU swasta tarifnya 0,3% dan untuk SPBU Pertamina tarifnya 0,25%;
[2] BBM jenis Solar, untuk SPBU swasta tarifnya 0,3% dan untuk SPBU Pertamina tarifnya 0,25%;
[3] BBM jenis Pertamax / Pertamax plus, untuk SPBU swasta tarifnya 0,3% dan untuk SPBU Pertamina tarifnya 0,25%;
[4] BBM jenis Minyak Tanah, untuk SPBU Pertamina tarifnya 0,3%;
[5] BBM jenis gas / LPG, untuk SPBU Pertamina tarifnya 0,3%;
[6] Pelumas Pertamina di SPBU Pertamina, tarifnya 0,3%
Maksud pemungutan ini untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Tetapi harus diingat bahwa kesederhanaan pemungutan pajak selalu berlawanan dengan keadilan. Sebagai contoh pengenaan PPh Final untuk industri migas. Kenapa perusahaan migas hanya membayar 0,25% dari penjualan? Bandingkan dengan industri dagang lain!
Sekilas ttg PPh 23
PPh Pasal 23 adalah jenis kredit pajak ke tiga. Masih banyak lagi jenis kredit pajak tetapi PPh Pasal 23 adalah yang paling banyak mengalami perubahan tarif dan jenis-jenis penghasilan. Penyebabnya adalah kewenangan yang diberikan UU PPh 1984 kepada Direktur Jenderal Pajak di Pasal 23 ayat (2) UU PPh 1984, yaitu “Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak”
Jenis jasa lain, penghasilan itulah yang sering berubah-ubah, kadang ditambah, kadang dikurangi. Bagi Wajib Pajak sendiri seharusnya tidak menjadi masalah apakah penghasilan yang dia terima dipotong PPh Pasal 23 atau tidak. Hanya saja, kebanyakan Wajib Pajak tidak mengetahui jika PPh Pasal 23 yang dipotong oleh fihak lain itu dapat dikreditkan di SPT PPh Tahunan. Jika kita tahu sedikit saja tentang tax planning maka pemotongan PPh Pasal 23 itu bisa menguntungkan.
Jenis penghasilan apa sajakah yang dipotong PPh Pasal 23? Berikut adalah perincian jenis pajak dan tarif efektif PPh Pasal 23 :
[1]. Deviden, tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan kotor
[2]. Bunga, tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan kotor
[3]. Royalti, tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan kotor
[4]. Hadiah dan penghargaan, tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan kotor
[5]. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, jumlahnya melebihi Rp.240.000 per bulan, tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan kotor [FINAL]
Berikut ini adalah kelompok penghasilan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak No. PER-70/PJ./2007 tanggal 9 April 2007
[6]. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, tarifnya 1,5% dari penghasilan kotor
[7]. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain kendaraan angkutan darat, untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[8]. Jasa teknik, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[9]. Jasa manajeman, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[10]. Jasa konsultansi, kecuali konsultansi konstruksi, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[11]. Jasa pengawasan konstruksi, tarifnya 4% dari penghasilan kotor
[12]. Jasa perencanaan konstruksi, tarifnya 4% dari penghasilan kotor
[13]. Jasa penilai, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[14]. Jasa aktuaris, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[15]. Jasa akuntansi, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[16]. Jasa perancang, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[17]. Jasa pengeboran (drilling) dibidang migas, kecuali dilakukan oleh BUT, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[18]. Jasa penunjang dibidang migas, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[19]. Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan selain migas, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[20]. Jasa penjunjang dibidang penerbangan dan bandar udara, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[21]. Jasa penebangan hutan, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[22]. Jasa pengolahan limbah, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[23]. Jasa penyedia tenaga kerja, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[24]. Jasa perantara, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[25]. Jasa perdagangan surat berharga, kecuali oleh bursa efek / KPEI / KSEI, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[26]. Jasa kustodian / penyimpanan / penitipan, kecuali oleh KSE, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[28]. Jasa pengisian suara, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[29]. Jasa mixing film, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[30]. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[31]. Jasa instalasi / pemasarang : peralatan, mesin, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, kecuali dilakukan oleh Wajib Pajak konstruksi bersertifikat, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[32]. Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan : peralatan, mesin, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi / kendaraan, bangunan, kecuali dilakukan oleh Wajib Pajak konstruksi bersertifikat, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[33]. Jasa pelaksana konstruksi, termasuk instalasi / pemasarang / perawatan / pemeliharaan / perbaikan : bangunan, peralatan, mesin, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, oleh Wajib Pajak konstruksi bersertifikat, tarifnya 2% dari penghasilan kotor
[34]. Jasa maklon, tarifnya 3% dari penghasilan kotor
[35]. Jasa penyelidikan dan keamanan, tarifnya 3% dari penghasilan kotor
[36]. Jasa penyelenggara kegiatan (EO), tarifnya 3% dari penghasilan kotor
[37]. Jasa pengepakan, tarifnya 3% dari penghasilan kotor
[38]. Jasa penyediaan tempat dan / atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi, tarifnya 1,5% dari penghasilan kotor
[39]. Jasa pembasmi hama, tarifnya 1,5% dari penghasilan kotor
[40]. Jasa kebersihan / cleaning servis, tarifnya 1,5% dari penghasilan kotor
[41]. Jasa catering, tarifnya 1,5% dari penghasilan kotor
Jenis jasa lain, penghasilan itulah yang sering berubah-ubah, kadang ditambah, kadang dikurangi. Bagi Wajib Pajak sendiri seharusnya tidak menjadi masalah apakah penghasilan yang dia terima dipotong PPh Pasal 23 atau tidak. Hanya saja, kebanyakan Wajib Pajak tidak mengetahui jika PPh Pasal 23 yang dipotong oleh fihak lain itu dapat dikreditkan di SPT PPh Tahunan. Jika kita tahu sedikit saja tentang tax planning maka pemotongan PPh Pasal 23 itu bisa menguntungkan.
Jenis penghasilan apa sajakah yang dipotong PPh Pasal 23? Berikut adalah perincian jenis pajak dan tarif efektif PPh Pasal 23 :
[1]. Deviden, tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan kotor
[2]. Bunga, tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan kotor
[3]. Royalti, tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan kotor
[4]. Hadiah dan penghargaan, tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan kotor
[5]. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, jumlahnya melebihi Rp.240.000 per bulan, tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan kotor [FINAL]
Berikut ini adalah kelompok penghasilan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak No. PER-70/PJ./2007 tanggal 9 April 2007
[6]. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, tarifnya 1,5% dari penghasilan kotor
[7]. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain kendaraan angkutan darat, untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[8]. Jasa teknik, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[9]. Jasa manajeman, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[10]. Jasa konsultansi, kecuali konsultansi konstruksi, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[11]. Jasa pengawasan konstruksi, tarifnya 4% dari penghasilan kotor
[12]. Jasa perencanaan konstruksi, tarifnya 4% dari penghasilan kotor
[13]. Jasa penilai, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[14]. Jasa aktuaris, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[15]. Jasa akuntansi, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[16]. Jasa perancang, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[17]. Jasa pengeboran (drilling) dibidang migas, kecuali dilakukan oleh BUT, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[18]. Jasa penunjang dibidang migas, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[19]. Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan selain migas, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[20]. Jasa penjunjang dibidang penerbangan dan bandar udara, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[21]. Jasa penebangan hutan, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[22]. Jasa pengolahan limbah, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[23]. Jasa penyedia tenaga kerja, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[24]. Jasa perantara, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[25]. Jasa perdagangan surat berharga, kecuali oleh bursa efek / KPEI / KSEI, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[26]. Jasa kustodian / penyimpanan / penitipan, kecuali oleh KSE, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[28]. Jasa pengisian suara, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[29]. Jasa mixing film, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[30]. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[31]. Jasa instalasi / pemasarang : peralatan, mesin, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, kecuali dilakukan oleh Wajib Pajak konstruksi bersertifikat, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[32]. Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan : peralatan, mesin, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi / kendaraan, bangunan, kecuali dilakukan oleh Wajib Pajak konstruksi bersertifikat, tarifnya 4,5% dari penghasilan kotor
[33]. Jasa pelaksana konstruksi, termasuk instalasi / pemasarang / perawatan / pemeliharaan / perbaikan : bangunan, peralatan, mesin, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, oleh Wajib Pajak konstruksi bersertifikat, tarifnya 2% dari penghasilan kotor
[34]. Jasa maklon, tarifnya 3% dari penghasilan kotor
[35]. Jasa penyelidikan dan keamanan, tarifnya 3% dari penghasilan kotor
[36]. Jasa penyelenggara kegiatan (EO), tarifnya 3% dari penghasilan kotor
[37]. Jasa pengepakan, tarifnya 3% dari penghasilan kotor
[38]. Jasa penyediaan tempat dan / atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi, tarifnya 1,5% dari penghasilan kotor
[39]. Jasa pembasmi hama, tarifnya 1,5% dari penghasilan kotor
[40]. Jasa kebersihan / cleaning servis, tarifnya 1,5% dari penghasilan kotor
[41]. Jasa catering, tarifnya 1,5% dari penghasilan kotor
Langganan:
Komentar (Atom)